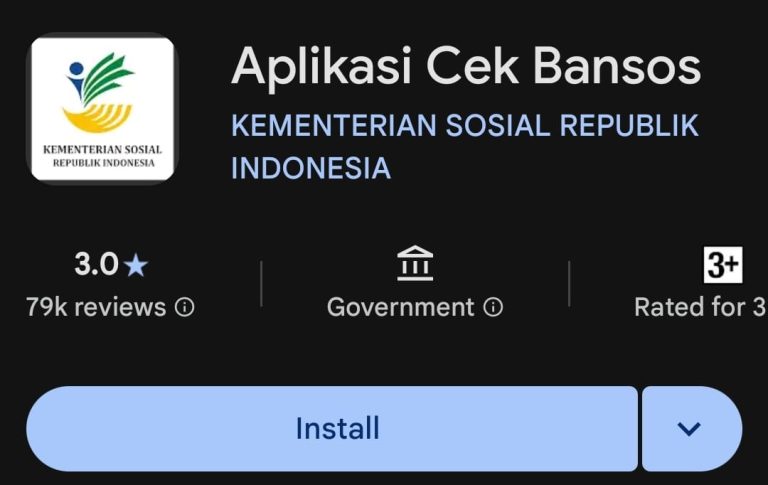Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Januari 2025 untuk menolak pilihan “tidak beragama” . Baik dalam kolom agama di KTP maupun KK. Hal ini kembali menegaskan satu pesan kuat. Bagi negara, warga negara Indonesia harus memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pernyataan itu wajib tercatat dalam administrasi kependudukan. MK bahkan menyebut permohonan untuk menambahkan kategori “tidak beragama” sebagai permohonan yang “tidak lazim”. Putusan tersebut seketika memantik kembali perdebatan panjang mengenai relasi antara negara, agama, dan kewarganegaraan.
Sebenarnya, persoalannya bukan sekadar teknis pencatatan. Kolom agama di KTP telah lama menjadi gerbang yang menentukan akses terhadap berbagai hak dasar sipil. Dari pencatatan pernikahan, pengakuan anak, pendidikan, kesehatan, hingga layanan perbankan. Bagi mayoritas warga yang memeluk agama resmi, keberadaan kolom itu mungkin terasa biasa saja. Tetapi bagi kelompok yang tidak berada dalam spektrum enam agama yang diakui negara. Termasuk mereka yang agnostik, ateis, atau memiliki pandangan spiritual di luar kategorisasi negara, kolom agama bukan sekadar kotak identitas, melainkan dinding yang membatasi akses sebagai warga negara.
Agnostik dan Atheis di Indonesia
Pengalaman personal yang mencuat ke media memperlihatkan bagaimana persoalan ini berlangsung di lapangan. Aika, seorang agnostik, terpaksa mempertahankan label “Kristen” di KTP karena tanpa itu ia tak dapat mencatatkan perkawinannya. Negara tidak menyediakan pernikahan sipil, sehingga pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama. Guruh, seorang ateis, terpaksa menikah dengan ritus Katolik demi memastikan kedudukan hukumnya sebagai ayah terhadap anaknya. Dalam kasus lain, anak penganut keyakinan di luar enam agama resmi dipaksa dicantumkan memeluk agama tertentu dalam kartu keluarga karena jika tidak, ia tidak dapat memperoleh layanan dasar pendidikan. Kasus-kasus seperti itu bukan anomali; ia cerminan struktur.
Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah: jika konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengapa negara tetap memaksa warga untuk memilih salah satu kategori agama dalam dokumen kependudukan?
Dalam pertimbangannya, MK berargumen bahwa pencatatan agama di KTP dan KK adalah bagian dari “perintah konstitusi” dan bukan pembatasan yang opresif. Negara, menurut MK, hanya meminta warga menyatakan agamanya untuk keperluan administrasi, tanpa mewajibkan ekspresi atau praktik keagamaan tertentu. Namun argumen tersebut menyisakan celah. Pertama, pencatatan agama dalam KTP tidak sekadar administratif karena berdampak langsung pada sah atau tidaknya pernikahan dan legitimasi keluarga berdasarkan hukum positif. Kedua, administrasi pendidikan, perbankan, hingga jaminan sosial masih sangat bergantung pada data kependudukan. Dalam struktur hukum semacam itu, ketiadaan agama bukan hanya “ketiadaan data”, melainkan ketidaklengkapan status kewarganegaraan.
Dalam konteks ini, sulit menepis pandangan para pegiat kebebasan beragama yang menyebut bahwa kolom agama pada akhirnya berfungsi lebih sebagai alat seleksi warga ketimbang instrumen pengakuan. Setara Institute, misalnya, menilai bahwa sejak awal kolom agama mengandung potensi diskriminatif karena memaksa warga untuk menempatkan dirinya dalam kategorisasi spiritual tertentu demi mengakses hak sipil. Dengan kata lain, negara menempatkan loyalitas administratif pada agama sebagai prasyarat untuk diakui sebagai warga negara sepenuhnya.
Sejarah Singkat Kolom Agama di KTP
Secara historis, relasi agama dan birokrasi kependudukan tidak berdiri di ruang kosong. Kolom agama pertama kali diwajibkan pada 1978 melalui TAP MPR Nomor IV/1978, pada masa ketika rezim Orde Baru membangun narasi anti-komunisme. Atheis, penghayat, dan kelompok spiritual yang tidak masuk dalam kategori agama resmi dicurigai sebagai “potensi ancaman”. Sejak itu, agama tidak lagi hanya menjadi kategori keimanan, tetapi menjadi penanda kesetiaan politik. Jejak itu masih dapat dilihat hingga hari ini.
Meski demikian, tidak semua perkembangan bersifat regresif. Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 pernah menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara mengakui aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Namun hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut masih formalistik. Penghayat memang dapat menuliskan “kepercayaan” dalam KTP, tetapi pengakuan administratif itu belum diikuti dengan perubahan substantif dalam layanan publik, kurikulum pendidikan, maupun sistem pencatatan pernikahan. Secara sosiologis, kepercayaan tetap ditempatkan sebagai “kategori toleransi”, bukan “kategori kesetaraan”. Di titik ini, penolakan terhadap pilihan “tidak beragama” kembali menghidupkan segregasi identitas yang sama: negara mengakui keberagamaan, tetapi masih belum siap mengakui ketidakberagamaan sebagai pilihan yang sah.
Perlukah Negara Mengatur Ekspresi Keagamaan Warga Negara?
Pertanyaannya kini bukan lagi “haruskah kolom agama dihapus?”. Tetapi “apakah negara bersedia memperlakukan keyakinan sebagai ranah pribadi. Bukan prasyarat kewarganegaraan?”. Negara dapat tetap menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa mengawasi ekspresi keagamaan warganya. Ia dapat tetap mendorong kehidupan beragama tanpa menjadikannya syarat legal untuk diakui sebagai warga negara.
Bila kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak. Maka pilihan untuk tidak beragama adalah bagian dari hak itu. Kewarganegaraan tidak boleh ditentukan oleh teologi. Melainkan oleh konstitusi, yang sebelum apa pun, seharusnya mengakui seluruh warga negara, tanpa diskriminasi keyakinan.
Selama kolom agama tetap menjadi mekanisme pembatas layanan sipil. Maka problem ini akan terus berulang, meski redaksinya berubah. Pada akhirnya, putusan MK membuka pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah negara siap memandang warganya sebagai manusia merdeka bukan sebagai objek kategorisasi keimanan?