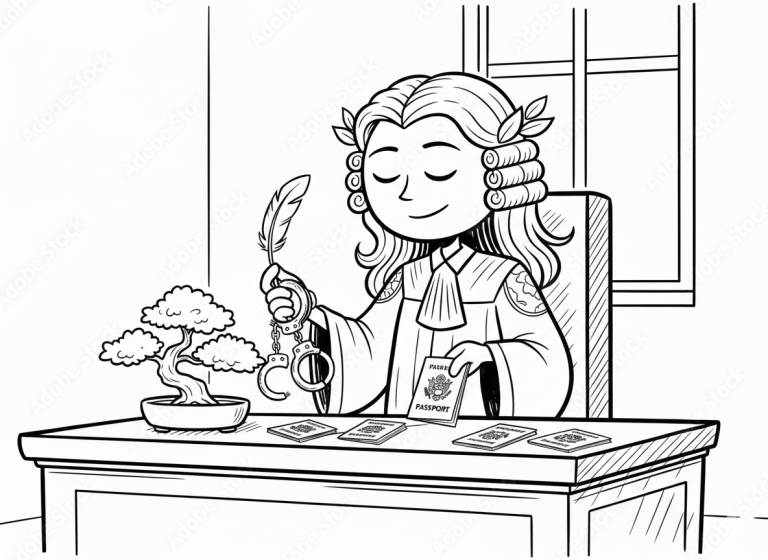Sumpah Pemuda 1928 dapat dipandang sebagai momen kelahiran kesadaran kewarganegaraan Indonesia. Sebab ia muncul dalam konteks masyarakat pra politik di jaman Hindia Belanda. Masa dimana identitas sosial ditentukan oleh ikatan etnis, daerah, atau agama. Di sisi lain, gagasan kewarganegaraan modern belum dikenal secara luas. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai suatu pembuka, niat awal, untuk mengkonstruksi satu bangsa di atas fondasi beragam bangsa dan bahasa yang ada. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda memang revolusioner. Ia menawarkan identitas kolektif baru yang melampaui politik segregasi kolonial, dengan tiga ikrar simbolik: berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu Indonesia. Sehingga dapat dikatakan Sumpah Pemuda adalah fondasi imajinasi politik “Indonesia”.
Namun dunia hari ini memaksa kita untuk meninjau kembali makna “Indonesia” dalam cakrawala global yang kian terbuka. Di tengah mobilitas manusia, krisis iklim, hingga transformasi digital yang mengaburkan yuridiksi nasional, makna kewarganegaraan tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka negara-bangsa tertutup. Sumpah Pemuda, bukan sekadar monumen sejarah, melainkan titik tolak untuk merefleksikan siapa yang diakui sebagai bagian dari “kita”, dan siapa yang masih ditempatkan di luar batas itu. Tinjauan berikut ini merupakan refleksi ketegangan antara visi 1928 dan realitas kita hari ini.
Kewarganegaraan dan Mobilitas Global
Pertama, dalam konteks globalisasi dan migrasi, kewarganegaraan kini bersifat transnasional. Banyak warga negara Indonesia hidup, bekerja, atau berkeluarga di luar negeri. Bukan tidak mungkin sebagian telah kehilangan kewarganegaraannya sehingga menjadi stateless. Umumnya karena persoalan-persoalan administrasi, seperti tidak melapor ke perwakilan untuk tetap menjadi warga negara, dan sebagainya. Di sisi lain, warga negara asing menetap di Indonesia dalam berbagai status. Mulai dari pekerja migran, digital nomad, hingga pengungsi. Sementara masyarakat adat, penganut agama lokal, sebagai “tuan rumah” masih ditempatkan di pinggiran.
Rekognisi negara masih sangat terbatas. Contohnya dalam kesetaraan beragama, negara masih membedakan antara yang disebut agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hak mencantumkannya pada kolom agama pun masih jadi fenomena baru dalam administrasi kependudukan. Itu pun masih dibumbui protes petinggi salah satu ormas keagamaan. Dalam realitas ini, “berbangsa satu” tidak cukup menjadi ikrar simbolik; ia harus diuji melalui komitmen terhadap inklusi hukum dan sosial, terutama bagi mereka yang rentan terhadap diskriminasi berbasis status kependudukan.
Mencintai Tanah Air, Mencintai Kelestarian Dunia
Kedua, krisis ekologis mengubah makna “bertumpah darah satu, tanah air Indonesia”. Kenaikan muka air laut, banjir, dan kekeringan tidak hanya mengancam wilayah teritorial, tetapi juga status kependudukan. Warga pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam, misalnya, menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal sekaligus dasar legalitas kependudukan mereka. Sementara itu, hukum nasional maupun internasional belum mengakui kategori “pengungsi iklim”, sehingga mereka yang terdampak bisa terjebak dalam jurang statelessness. Dalam pengertian ini, Sumpah Pemuda perlu ditafsir ulang sebagai janji kolektif untuk melindungi hak atas tanah, air, dan tempat tinggal—bukan hanya sebagai simbol nasionalisme, tetapi sebagai prasyarat dasar kewarganegaraan yang bermartabat.
Lebih jauh, definisi “warga negara yang baik” sering kali dikaitkan dengan standar-standar yang ditentukan agama mayoritas. Akibatnya, warga negara yang beragama minoritas, bahkan yang beragama lokal (penghayat kepercayaan), kerap diposisikan sebagai “warga negara kelas dua.” Meski secara hukum seluruhnya memiliki status yang setara. Tapi membangun tempat ibadah masih menjadi persoalan, kolom agama di KTP masih dibedakan. Ini menunjukkan tumpah darah yang satu, belum sepenuhnya dipahami sebagai rumah bersama. Melainkan masih dikontestasikan untuk dominasi.
Indonesia: Ius Sanguinis Kuat
Ketiga, meski Sumpah Pemuda menawarkan visi persatuan, proses pembentukan identitas nasional juga membawa serta bentuk-bentuk hegemoni. Penetapan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa nasional, misalnya, meski strategis untuk membangun solidaritas antaretnis, juga berkontribusi pada marginalisasi bahasa daerah dan budaya lokal. Posisi menjunjung bahasa persatuan, harus dimaknai juga melestarikan bahasa-bahasa daerah pembentuknya.
Fenomena anak-anak hasil perkawinan campuran, yang jelas separuh darahnya adalah Indonesia contohnya. Jika konsisten dengan prinsip ius sanguinis yang kita anut, maka posisi Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas adalah: Anak Indonesia yang diberikan hak berkewarganegaraan ganda terbatas. Sebagian besar bisa berbahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Mereka bukan orang asing berkewarganegaraan ganda terbatas. Posisi ini tampak tidak adil jika dibandingkan apa yang disebut “pemain diaspora” yang darah Indonesianya berasal dari kakek atau nenek. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia masih terbatas. Prosesnya pewarganegaraannya, jauh lebih mudah dan cepat, semata-mata karena kebutuhan olahraga nasional. Kewarganegaraan bukan sesuatu yang patut dikomodifikasi, ia soal kecintaan, keterikatan, dan perasaan seseorang. Baik “pemain diaspora” maupun anak hasil perkawinan campuran, sama-sama berdarah Indonesia. Bukankah seharusnya kita perlakukan sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang setara juga?
Sumpah Pemuda dan Perubahan UU Kewarganegaraan
Maka, merayakan Sumpah Pemuda di tahun 2025 bukan hanya soal mengenang semangat 1928. Akan tetapi juga menengok kembali batas-batas yang masih menghambat realisasi kewarganegaraan yang inklusif, adil, dan setara. Di tengah dunia yang semakin terhubung namun penuh ketimpangan, menjadi warga negara Indonesia berarti tidak hanya berakar pada tanah air. Melampaui itu, kita juga harus bisa menjadi warga dunia yang beradab, dan partisipatif. Mencintai tanah air umat manusia yaitu dunia yang kita tempati bersama.
Sedangkan dalam konteks kewarganegaraan, DPR tengah mempersiapkan perubahan UU Kewarganegaraan. Prinsip penting yang harus diperhatikan para wakil rakyat adalah jangan sampai seorang WNI dengan mudah kehilangan kewarganegaraannya. Apalagi hanya karena sebab-sebab administratif atau tidak atas kehendak sendiri. UU ke depan juga seharusnya dapat memberikan jalan keluar yang lebih mudah bagi eks-WNI jika ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Bedakan dengan naturalisasi WNA murni. Pada momentum Sumpah Pemuda ini, mari teguhkan komitmen agar tidak ada seorang pun saudara sebangsa setanah air tertinggal di luar batas imajinasi kewarganegaraan kita.@esa