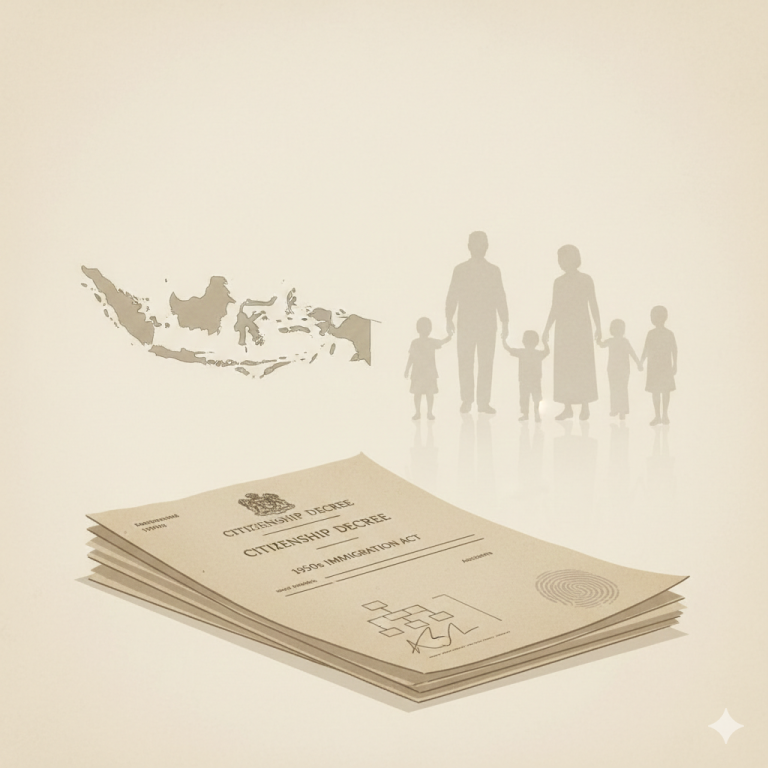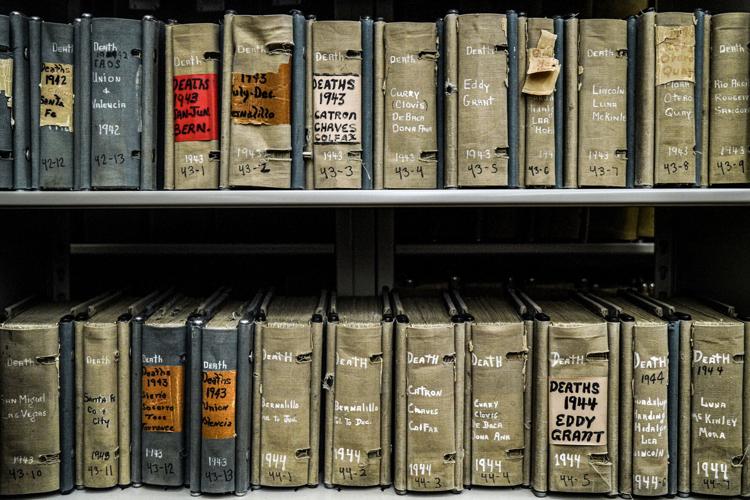Kewarganegaraan di Indonesia bukan sekadar status hukum. Ia adalah kunci pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang sebagai bagian dari komunitas nasional. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, bahkan perlindungan hukum. Di Indonesia, hak atas kewarganegaraan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Namun, di balik jaminan tersebut, masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dalam memperoleh atau mempertahankan status kewarganegaraan.
Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia lalu mengesahkan Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan pertamanya, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Namun sayangnya, meski mencantumkan istilah Penduduk Negara pada judul UU tapi regulasi ini hanya menyebut 1 pasal tentang penduduk. Sehingga untuk administrasi kependudukan, memang belum diatur pada saat itu. Pemerintah hanya meneruskan warisan administrasi kependudukan kolonial Belanda. Berdasarkan regulasi ini, semua penduduk Hindia Belanda kecuali golongan Eropa baik totok maupun peranakan, ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia, disingkat WNI. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini, diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1947. Dalam PP ini, secara jelas dinyatakan bahwa:
“…dalam sistem undang-undang warga negara Indonesia, suatu bukti kewargaan negara Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi warga negara Indonesia, yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan. Maka, bukti kewargaan negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya, bukan warga negara Indonesia, yaitu kepada orang asing yang menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi”.
Dinamika RI – Belanda
Dinamika hukum kewarganegaraan di Indonesia, selanjutnya beriringan dengan relasi Indonesia dengan beberapa negara. Belanda sebagai bekas penjajah, lalu Tiongkok terkait dengan dwikewarganegaraan sebagai konsekuensi lahirnya negara Tiongkok modern pada 1949.
Dinamika pertama adalah hasil Konferensi Meja Bundar pada 1949. Dimana salah satu kesepakatannya adalah Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia dan Belanda. Pada pembagian ini, diterapkan stelsel pasif untuk penduduk Hindia Belanda dari golongan Timur Asing yaitu Tionghoa, India, dan Arab. Sementara untuk golongan Eropa stelsel aktif. Artinya golongan pertama cukup diam untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan golongan kedua, harus aktif mendaftarkan diri kalau mau menjadi WNI.
Dinamika RI – Tiongkok
Selanjutnya, dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1949, terjadi dinamika kedua. Hal ini mulai dibahas menjelang Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Pada KAA tersebutlah dicapai kesepakatan tentang Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT disingkat PDK. Obyeknya adalah orang-orang Tionghoa yang dinilai masih berkewarganegaraan ganda. Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar orang Tionghoa sudah dinyatakan sebagai WNI Tunggal, dan bukan obyek perjanjian. Selanjutnya kedua negara bersepakat bahwa masa memilih bagi mereka pada 1960-1962, untuk yang sudah dewasa. Bagi yang masih anak-anak, kelak dapat memilih hingga 1980.
Gangguan terhadap PDK
Perjanjian ini tampak jelas dan baik, tapi sayang setelah Indonesia mengalami masa darurat akibat pemberontakan DI/TII, hingga Permesta, UUD 1945 diganti. Hal ini konsekuensi dari kesepakatan KMB, bahwa Indonesia yang diakui berbentuk serikat. Maka UUDS 1950 adalah persiapan UUD RIS. UU Kewarganegaraan pun diganti dengan UU Nomor 62 Tahun 1958. Selanjutnya, terjadi gangguan tepat di akhir 1959 hanya sebulan sebelum pelaksanaan PDK. Indonesia ketika itu menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1959.
Regulasi yang lebih akrab disebut PP 10 ini, mengatur larangan perdagangan kecil/eceran yang bersifat asing di luar daerah swatantra tingkat I dan II. Sederhananya WNA dilarang punya usaha eceran di desa dan kecamatan. Sekali lagi, ini aturan yang baik untuk mendukung perekonomian kecil di perdesaan. Akan tetapi implementasinya oleh militer, jauh panggang daripada api.
Kegemparan terjadi di perdesaan, karena militer menyasar semua orang Tionghoa yang telah hidup turun temurun disana. Orang-orang Tionghoa di perdesaan umumnya memang memiliki usaha eceran, tapi mereka juga umumnya bertani, beternak sebagaimana penduduk desa lainnya. Pekerjaan demikian termasuk yang dianggap telah menjadi WNI Tunggal. Tapi tiba-tiba mereka diusir dan terpaksa pindah ke daerah perkotaan. Selanjutnya mereka bahkan diberikan satu dokumen pengusiran, yaitu Exit Permit Only (EPO). Tiket satu arah keluar dari tanah airnya.
Perjalanan Panjang Memperoleh Kewarganegaraan
Peristiwa inilah yang melahirkan beberapa kampung Indonesia di Tiongkok. Kampung yang didirikan oleh sebagian kecil yang terangkut oleh beberapa kapal, yang dikirim Tiongkok setelah peristiwa tersebut. Hingga kini mereka masih fasih berbahasa daerah atau bahasa Indonesia, dan tinggal di kampung Bali, dan kampung Indonesia lainnya.
Mereka yang tidak pergi, kemudian melalui perjalanan panjang berliku mengurus berbagai dokumen karena dianggap asing. Walau secara yuridis, mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai orang asing. Hanya memegang dokumen buatan pemerintah Indonesia yaitu EPO. Bertahun-tahun orang-orang Tionghoa terlunta-lunta dengan status kewarganegaraan menggantung. Apalagi kemudian terjadi peristiwa 1965, yang memperburuk situasi. Apalagi hubungan RI-RRT pun memburuk, hingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik.
Perubahan geopolitik dan Stabilitas Rezim Orba
Dalam proses menuju normalisasi hubungan, ada dua tahap penting yang dilalui Indonesia dan Tiongkok. Pada periode pertama, antara tahun 1970 hingga 1977, Tiongkok cukup aktif mengambil inisiatif. Mereka menawarkan bantuan, menunjukkan dukungan terhadap stabilitas kawasan, hingga mengundang atlet dan pengamat dari Indonesia untuk berkunjung ke negaranya. Meski begitu, Indonesia tetap menjaga jarak. Pemerintah saat itu memilih menolak pendekatan Tiongkok demi menjaga stabilitas dalam negeri.
Memasuki tahap berikutnya, dari tahun 1977 hingga 1988, pendekatan Tiongkok mulai bergeser ke jalur ekonomi. Titik awalnya adalah kunjungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ke Canton Fair pada 1977, yang membuka peluang untuk kerja sama yang lebih konkret. Hubungan ekonomi ini semakin menguat setelah pada 24 November 1984, Indonesia membuka jalur perdagangan lewat pelabuhan Hongkong. Tak lama kemudian, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1985 mempertegas langkah ini. Pada 23 Juli 1985, hubungan dagang langsung antara Indonesia dan Tiongkok pun resmi dimulai.
Sementara di dalam negeri, rezim Suharto dengan struktur penopang kekuasaan ABRI, Birokrasi, dan Golkar, sudah kokoh. Sekber Golkar sejak pertama orba pada 1971, telah mendominasi perolehan suara. Golkar menguasai 236 kursi dari 360 kursi tersedia. Artinya, lebih dari 50% kursi DPR berhasil dikuasai ormas yang baru pertama kali ikut pemilu. Suharto-Orba kemudian melakukan penyederhaan partai politik pada 1973, hingga tersisa 2 partai politik dan 1 ormas, yaitu Golkar. Kembali pada Pemilu 1977, Golkar makin dominan dengan perolehan 62,11% suara, meski secara kursi turun ke 232 dari 360 kursi yang diperebutkan. Hal ini tampaknya menambah keyakinan dalam membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok.
Dampak Pada Dinamika Kewarganegaraan Tionghoa
Perubahan geopolitik yang memungkinkan terjalinya kembali hubungan diplomatik antara RI dan Tiongkok, turut berdampak terhadap upaya penyelesaian status kewarganegaraan. Dimana pasca membaiknya hubungan diplomatik dengan Tiongkok, upaya penyelesaian permasalahan kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang “mengambang” dimulai. Secara teoritis, status mereka dapat dikategorikan sebagai de facto stateless, karena secara hukum mereka WNI namun tidak efektif kewarganegaraannya, akibat persoalan administrasi semata. Diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan RI, yang berhasil menerbitkan sekitar setengah juta Surat Bukti Kewarganegaraan RI dsiingkat SBKRI.
Ironisnya, baik pada peraturan pelaksanaan UU Kewarganegaraan pertama sebagaimana disebut di atas. Maupun pada UU kewarganegaraan kedua, yaitu UU No. 62 Tahun 1958, pada Pasal IV Penutup yang menyatakan:
“Surat bukti yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia hanya diperuntukkan bagi mereka yang merasa perlu membuktikan kewarganegaraannya tanpa menjadi kewajiban”.
Bahkan ditegaskan dalam penjelasan UU melalui Pasal 2 PP Nomor 67 Tahun 1958:
“Dalam hal ini perlu pula diterangkan bahwa Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut hanya dapat dipergunakan bilamana pembuktian yang dimaksud diperlukan , hal mana harus dibuktikan dengan adanya pernyataan suatu instansi jawatan yang meragukan status orang yang berkepentingan.”
Tidak Butuh Bukti Tapi Diminta
Jadi sebenarnya secara hukum, warga negara tidak wajib punya surat bukti kewarganegaraan. Akan tetapi, jika ada instansi yang meragukan kewarganegaraan seseorang, instansi tersebutlah yang pertama-tama harus membuat pernyataan tentang keraguannya itu. Hal yang tidak pernah terjadi selama masa orde baru, instansi yang meragukan tidak pernah membuat pernyataan. Sedangkan masyarakat Tionghoa disudutkan dan dituntut punya bukti kewarganegaraan, sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.
Parahnya lagi, setelah memiliki SBKRI pun ternyata diskriminasi masih berlanjut. Mulai dari proses yang berbiaya tinggi akibat praktik pungli oknum di berbagai daerah, hingga tindakan mempersulit proses pengurusan yang ujung-ujungnya uang juga. Pemerintah orde baru sebenarnya mulai menyadari kekeliruan ini, dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 4 ayat (2) keppres tersebut menyatakan:
“Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran tersebut.”
UU Kewarganegaraan Reformasi
Persoalan diskriminasi terhadap WNI Tionghoa ini, juga menjadi perhatian pada masa awal reformasi. Di alam keterbukaan demokrasi dan mulai diintrodusirnya Hak Asasi Manusia, Presiden BJ Habibie mengambil langkah tegas. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres 56 Tahun 1996, ditegaskan dengan keluarnya keppres pada 1996 tersebut, semua peraturan perundangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku.
Dalam UU No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara:
-
Kelahiran dari orang tua WNI
-
Pengangkatan anak oleh orang tua WNI
-
Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
-
Perkawinan campuran
-
Pemberian kewarganegaraan oleh negara
-
Pendaftaran bagi anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas
Regulasi ini juga mengatur tentang kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan, serta perlindungan terhadap anak-anak tanpa kewarganegaraan (stateless).
Tantangan di Lapangan
Meskipun aturan hukum sudah jelas, tantangan di lapangan tetap nyata. Berikut beberapa isu utama:
1. Anak Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Children)
Anak hasil perkawinan campuran, anak dari orang tua tidak berdokumen, atau anak yang lahir di luar negeri kerap menghadapi status tidak jelas. Banyak dari mereka tak dapat mengakses layanan dasar karena tak punya bukti kewarganegaraan.
Baca: Laporan Statistik UNHCR 2021
2. Warga Negara Ganda Terbatas
Anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun + 1. Jika tidak memilih kewarganegaraan pada saat itu, ia bisa kehilangan keduanya.
3. Permohonan Naturalisasi yang Kompleks
Warga asing yang telah lama tinggal di Indonesia dan berkontribusi secara sosial atau ekonomi sering menghadapi prosedur yang rumit dan waktu yang lama untuk menjadi WNI.
4. Kurangnya Akses Informasi dan Pendampingan
Banyak masyarakat rentan tidak mengetahui haknya untuk memperoleh kewarganegaraan atau prosedur yang harus dilalui. Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil menjadi penting.
Negara dan Masyarakat Sipil
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin setiap individu memiliki kewarganegaraan. Namun, implementasi di lapangan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.
Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia secara aktif:
-
Memberikan pendampingan hukum dan administratif untuk kasus kehilangan atau ketidakjelasan status kewarganegaraan
- Mendampingi masyarakat tidak mampu dan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya untuk memperoleh dokumen identitas hukum.
-
Mendorong reformasi kebijakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan
-
Mengedukasi masyarakat melalui pelatihan, publikasi, dan advokasi publik
Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Jika Anda mengalami masalah kewarganegaraan, cari bantuan dari lembaga layanan atau hubungi kami.
-
Jika Anda seorang pendidik, relawan, atau profesional hukum, ikutlah dalam kampanye literasi hukum tentang kewarganegaraan.
-
Jika Anda seorang pengambil kebijakan, doronglah kebijakan yang inklusif dan menghargai hak asasi warga negara.
Penutup: Kewarganegaraan Adalah Hak, Bukan Hadiah
Hak atas kewarganegaraan adalah fondasi utama dari semua hak lainnya. Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan seseorang hidup di tanah airnya sendiri tanpa diakui sebagai warga. Mari bersama-sama memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, dan bahwa setiap orang di Indonesia dapat hidup sebagai warga negara yang setara dan bermartabat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor:
3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara