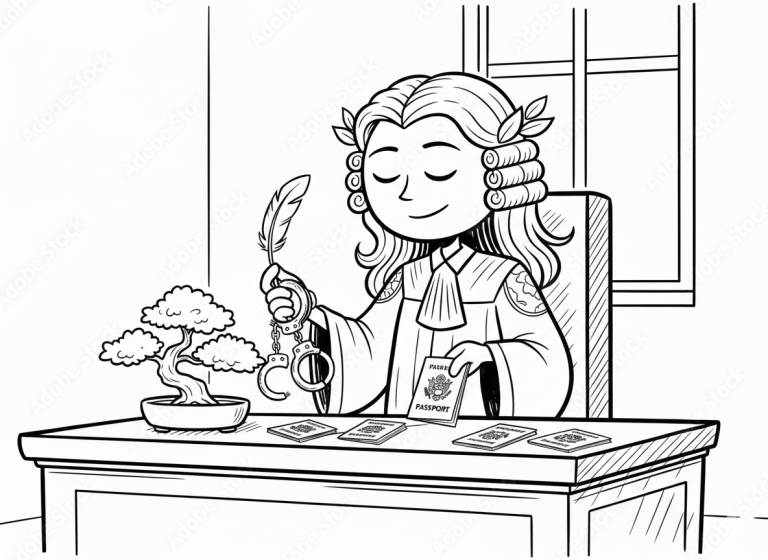Lebih dari satu dekade setelah puncak krisis migrasi 2015, Eropa masih bergulat dengan warisan kebijakan yang belum tuntas. Arus kedatangan migran memang kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh perang di Ukraina, ketidakstabilan di Afrika dan Timur Tengah, serta dampak krisis iklim. Namun tantangan integrasi utama bukanlah sekadar jumlah migran baru. Masalah sesungguhnya terletak pada kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan mereka yang telah lama tinggal di benua ini.
Gelombang Migrasi ke Eropa
Data menunjukkan bahwa jumlah kedatangan ilegal di wilayah Uni Eropa pada 2023 mencapai level tertinggi sejak 2016. Namun, angka itu tidak menceritakan seluruh kisah. Di balik statistik tersebut tersembunyi realitas yang lebih kompleks: Eropa sedang menanggung beban dari respons yang reaktif, fragmentatif, dan sering kali tidak manusiawi terhadap migrasi selama satu dekade terakhir. Banyak migran yang tiba pada 2015–2016 masih hidup dalam ketidakpastian hukum, terpinggirkan secara ekonomi, atau terjebak dalam segregasi sosial. Bukan karena mereka menolak berintegrasi, tetapi karena sistem yang seharusnya mendukung mereka justru menghambat.
Pada Maret 2024, Uni Eropa akhirnya mengesahkan Pact on Migration and Asylum. Suatu kerangka kebijakan ambisius yang bertujuan menyatukan pendekatan negara-negara anggota dalam menangani migrasi. Pakta ini menjanjikan mekanisme pembagian tanggung jawab yang lebih adil, prosedur suaka yang lebih cepat, serta penguatan kerja sama dengan negara asal dan transit. Namun, para kritikus, termasuk organisasi hak asasi manusia, mengingatkan bahwa banyak ketentuannya justru memperkuat pendekatan keamanan (securitisation). Dan meminggirkan prinsip non-refoulement. Yang lebih mengkhawatirkan, pakta ini tidak secara eksplisit menempatkan integrasi sebagai prioritas strategis. Melainkan sebagai urusan sekunder yang diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota.
Kegagalan Proses Integrasi
Padahal, integrasi bukanlah proses satu arah yang memaksa migran “menjadi Eropa”. Ia adalah dialog timbal balik: antara nilai universal yang menjadi fondasi Uni Eropa. Yakni nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial. Selain itu juga keragaman latar belakang yang justru memperkaya identitas kolektif benua ini. Sayang, dalam praktiknya, integrasi sering kali direduksi menjadi syarat birokratis: kursus bahasa, ujian kewarganegaraan, atau larangan berpakaian tertentu. Sementara itu, akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, dan partisipasi politik yang merupakan pilar-pilar nyata kewarganegaraan, masih jauh dari merata.
Kegagalan ini diperparah oleh absennya solidaritas internal Uni Eropa. Negara-negara di garis depan seperti Yunani, Italia, dan Spanyol terus menanggung beban tidak proporsional. Sementara negara-negara lain menolak berbagi tanggung jawab dengan alasan melindungi “identitas nasional”. Akibatnya, kebijakan migrasi Eropa terpecah-pecah, inkonsisten, dan rentan dimanfaatkan oleh narasi populis. Narasi yang menjadikan migran sebagai kambing hitam atas krisis ekonomi atau sosial domestik.
Padahal, kaum migran, jika diberi ruang yang adil, tentu bukan beban melainkan aset. Di Jerman, sektor perawatan kesehatan dan manufaktur sangat bergantung pada tenaga kerja migran. Di Prancis dan Belanda, generasi kedua migran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya, ilmu pengetahuan, dan politik. Namun, potensi ini hanya bisa tumbuh dalam iklim kepercayaan, bukan dalam atmosfer kecurigaan yang dibangun oleh retorika politik eksklusif.
Kewarganegaraan Inklusif
Dari perspektif Indonesia, negara yang dibangun di atas kebhinekaan. Tantangan integrasi Eropa ini mengingatkan kita pada prinsip dasar kewarganegaraan inklusif: keanggotaan dalam suatu komunitas politik tidak ditentukan oleh etnisitas, agama, atau asal-usul. Akan tetapi, oleh komitmen bersama terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Eropa perlu kembali ke akar filosofisnya: bahwa identitas Eropa bukanlah identitas eksklusif, melainkan proyek moral yang terbuka.
Jurnalisme, pendidikan, dan diplomasi budaya memiliki peran penting dalam menggeser narasi. Alih-alih menggambarkan migran sebagai ancaman, media dan pemimpin publik harus menampilkan mereka sebagai sesama warga yang sedang membangun masa depan bersama. Tentu dengan harapan, kontribusi, dan hak yang sama.
Eropa kini tidak sedang menghadapi “gelombang baru”, melainkan sedang berdiri di hadapan cermin. Sambil merenungkan, apakah ia masih mampu mempertahankan nilai-nilai humanis yang selama ini ia gemakan di panggung global? Jawabannya tidak terletak pada tembok perbatasan atau kebijakan represif, tapi pada kemampuannya untuk membuka ruang—ruang kerja, ruang politik, ruang budaya—bagi mereka yang memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Eropa itu sendiri.
Kebenaran bukan hanya soal fakta, tapi juga soal rasa dan nurani. Tanpa itu, tantangan integrasi bisa jadi akan selalu gagal. Bukan karena migrannya, tetapi karena ketidakmauan Eropa untuk menjadi dirinya sendiri: rumah bagi semua yang percaya manusia dan kemanusiaan.@esa