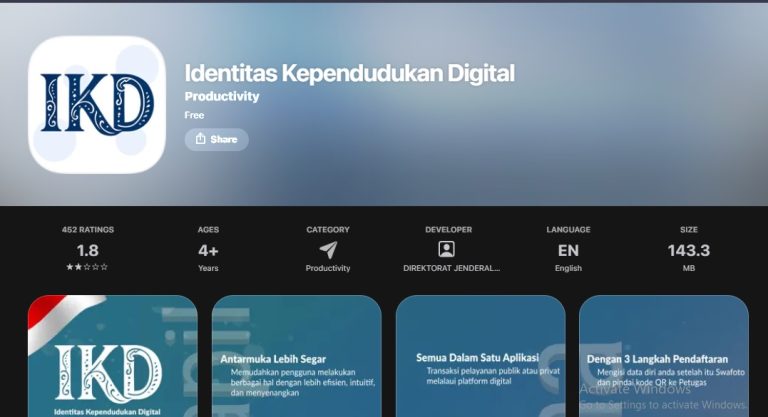The Japan Times baru-baru ini memuat sebuah tulisan reflektif oleh Jon Heese. Mantan anggota Majelis Kota Tsukuba dan kini anggota Majelis Prefektur Ibaraki. Refleksinya berjudul “Why I Chose Japanese Citizenship Over Permanent Residency: Dual Citizenship Would Be Great, But the Reality Is Permanent Residency Just Isn’t Enough.” Artikel tersebut diterbitkan pada 17 Oktober 2025 lalu. Di dalamnya, Heese yang telah menjadi warga negara Jepang pada tahun 2007. Memberikan alasan personal dan politis di balik keputusannya meninggalkan kewarganegaraan Kanada, dan sepenuhnya menjadi warga Jepang.
Pandemi Covid dan Pilihan Naturalisasi
Heese membuka tulisannya dengan pengakuan bahwa setelah lebih dari tiga dekade hidup di Jepang, ia menyadari dirinya akan menetap seumur hidup. Karena itu, ia menilai izin tinggal permanen (permanent residency) tidak memberikan jaminan yang cukup, terutama ketika situasi darurat terjadi. Ia menyinggung contoh konkret saat pandemi COVID-19 pada 2020. Ketika pemerintah Jepang tiba-tiba menutup perbatasan bagi warga asing, termasuk pemegang izin tinggal permanen. “Hanya pemegang paspor Jepang yang diizinkan masuk” tulisnya. Hal ini menegaskan bahwa hak penuh untuk kembali ke negara tempat tinggal hanya dimiliki oleh warga negara. Bukan penduduk tetap.
Menariknya, Heese juga menyoroti bagaimana kewarganegaraan di abad modern telah mengambil posisi seperti agama. Menjadi semacam identitas sosial dan emosional yang menentukan rasa kebersamaan. Ia membandingkan reaksi teman-teman sesama warga asing saat ia memilih menaturalisasi dengan pengalaman masa kecilnya di Saskatchewan, Kanada. Perasaannya sama seperti perasaan anggota gereja yang tersisa, ketika anggota lainnya meninggalkan gereja. Perasaan dicampakkan.
Antara Uchi dan Soto
Dalam tulisannya, Heese mengaitkan refleksi pribadinya dengan konsep Jepang tentang “uchi” (dalam, kelompok sendiri) dan “soto” (luar, orang asing). Menurutnya, menjadi warga negara Jepang berarti berpindah dari satu “suku” ke suku lain. Keputusan yang secara sosial dan emosional tidaklah sederhana. Ia juga mengutip Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo). Penulis era Meiji, yang pernah menyebut bahwa “ke-Jepang-an” sendiri adalah semacam “agama nasional.”
Meski begitu, Heese menegaskan bahwa melakukan naturalisasi bukan berarti meninggalkan identitas asal sepenuhnya. Ia masih mendukung tim sepak bola asal provinsi kelahirannya, Saskatchewan Roughriders. Demikian juga ia tetap diterima di komunitas warga asing di Jepang. Namun, menjadi warga negara Jepang memberi rasa aman yang berbeda: tidak ada lagi pemeriksaan berlebih di imigrasi, tidak ada keraguan soal hak tinggal, dan tidak ada ketakutan akan penolakan masuk ke negara tempat ia menetap.
Heese mengakui bahwa ia lebih memilih kewarganegaraan ganda jika Jepang mengizinkannya. Namun sampai saat itu terjadi, ia menilai naturalisasi adalah langkah yang logis dan aman bagi siapa pun yang benar-benar menganggap Jepang sebagai rumah. Ia juga menegaskan bahwa proses naturalisasi tidak serumit yang dibayangkan. Cukup lima tahun tinggal di Jepang, memiliki penghidupan stabil, dan mampu berbahasa Jepang tingkat menengah.
Di akhir tulisannya, Heese menyampaikan rasa optimistis terhadap masa depan Jepang: dari menghadapi krisis demografis, kekurangan tenaga kerja, hingga pengembangan teknologi dan kebijakan sosial. “Saya bersyukur bisa menyaksikan semuanya dari barisan depan,” tulisnya. “Karena saya tahu, izin tinggal permanen saja tidak cukup.”
Tulisan ini memberikan perspektif menarik dari seorang warga naturalisasi yang melihat kewarganegaraan bukan sekadar status hukum, melainkan pernyataan komitmen terhadap masa depan negeri yang ia pilih untuk disebut rumah.@esa