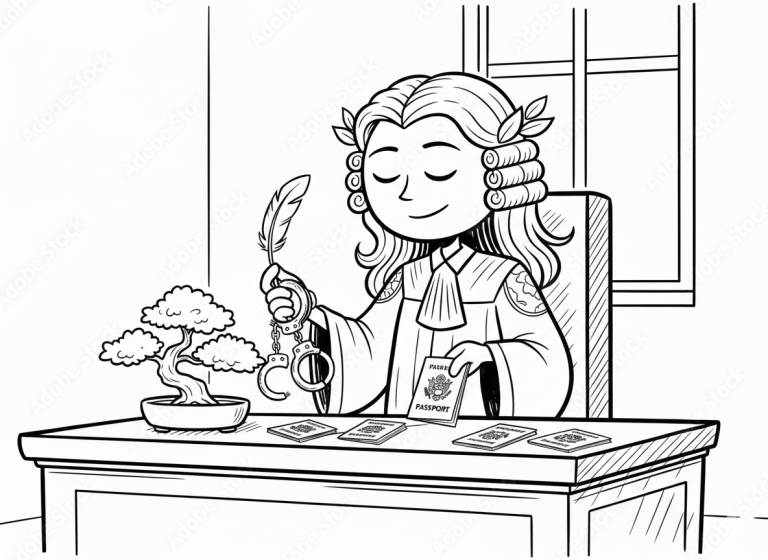Nama Penulis Opini : M. Yunasri Ridhoh
Email Penulis Opini : yunasri.ridhoh@unm.ac.id
Polemik kewarganegaraan ganda sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam percakapan kewargaan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, ketika Indonesia memilih kewarganegaraan tunggal sebagai prinsip kewargaannya, sejak saat itulah isu ini menjadi polemik. Lalu bagaimana dengan GCI? Apakah ia adalah jalan tengah diantara polemik tersebut?
Saat itu pilihan kewargaan tunggal sangat bisa dipahami, tidak lain adalah untuk menjaga kedaulatan negara, loyalitas warga, serta kepastian hukum. Prinsip itu disepakati atas dasar konteks sejarah yang tidak sederhana, disana ada pengalaman kolonialisme, pergulatan identitas nasional, serta kebutuhan membangun negara-bangsa yang solid.
Namun, dunia telah berubah secara drastis. Mobilitas manusia lintas negara semakin tinggi, perkawinan campuran juga meningkat. Lalu terjadi diaspora Indonesia yang kian tumbuh besar di berbagai belahan dunia. Dalam situasi inilah negara dituntut untuk merespons realitas kewargaan yang tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan oleh batas-batas kewarganegaraan formal.
Jalan Tengah
Peluncuran kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) menjadi penanda bahwa negara mulai mencari bentuk baru dalam mengelola persoalan kewargaan. GCI menawarkan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi orang asing yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia, misalnya mantan Warga Negara Indonesia (WNI), keturunan WNI, pasangan WNI, atau anak dari perkawinan campuran, tanpa mewajibkan mereka untuk merubah kewarganegaraannya.
Kebijakan ini diposisikan sebagai solusi kompromis dan akomodatif untuk menjawab tuntutan diaspora dan keluarga transnasional, sembari tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal. Apakah ini akan menjadi solusi substantif? bolehjadi, tapi mungkin juga tidak, karenanya sementara ini masih menjadi perdebatan.
Terlepas dari polemik itu, lahirnya GCI patut dibaca sebagai upaya negara mencari jalan tengah antara dua kepentingan yang acapkali dianggap bertentangan, yakni menjaga kedaulatan hukum kewarganegaraan dan merespons realitas mobilitas global. Dalam paradigma lama, kewarganegaraan dipahami sebagai relasi eksklusif antara seseorang dan negara. Disini seseorang harus memperjelas, apakah ia warga negara, atau ia adalah orang asing. Itu mesti jelas, tidak ada ruang abu-abu.
GCI sebagai Jalan Tengah yang Pragmatis?
Sementara GCI secara implisit hadir dan mengakui bahwa ruang abu-abu itu mesti diakomodir. Sebab kini keadaan telah berubah dan keadaan itu kian nyata dan tidak terelakkan. Saat ini ada banyak orang yang memiliki keterikatan emosional, kultural, sosial, dan ekonomi yang kuat dengan suatu negara. Misalnya dengan Indonesia, meski secara hukum bukan lagi WNI. Dengan memberi izin tinggal tetap tanpa batas waktu. Negara mengakui bahwa kontribusi dan keterikatan tidak selalu harus dibuktikan dengan paspor hijau.
Dari sudut pandang kebijakan publik, GCI ini juga dapat dibaca sebagai langkah pragmatis. Dimana negara tidak perlu mengubah undang-undang kewarganegaraan atau membuka perdebatan politik yang sensitif di parlemen. Prinsip kewarganegaraan tunggal tetap utuh dan dipertahankan, sementara kebutuhan praktis diaspora dan keluarga campuran tetap diakomodasi melalui rezim keimigrasian.
Pendekatan ini sekaligus memberi pesan bahwa negara bersedia beradaptasi tanpa kehilangan kendali dan prinsip. Dalam konteks global yang kadang dikepung ketidakpastian, pendekatan moderat semacam ini memang dirasa solutif, sebab lebih aman secara hukum, lalu relatif lebih rendah risiko politik, dan dapat diklaim sebagai inovasi kebijakan.
Kritik Diaspora dan Batas Solusi Administratif
Sejak diumumkan, GCI tidak lepas dari kritik, terutama dari kalangan diaspora. Kritik utama berkisar pada anggapan bahwa GCI belum menyentuh substansi kewarganegaraan ganda. Izin tinggal tetap, betapapun permanennya, tetap saja berbeda secara prinsipil dari status kewarganegaraan.
Sebab pemegang GCI tidak memiliki hak politik, tidak memiliki jaminan penuh dalam kepemilikan aset tertentu, serta tetap berada dalam posisi yang secara hukum lebih lemah dibanding warga negara. Disana mereka mesti tunduk pada kebijakan keimigrasian yang sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa perlindungan konstitusional yang melekat pada status kewarganegaraan.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa GCI justru berisiko menjadi kebijakan yang elitis. Jika prosedur rumit dan biaya tinggi, maka hanya segelintir diaspora, misalnya hanya profesional global, investor besar, atau individu berpenghasilan tinggi, yang dapat mengaksesnya. Padahal, banyak mantan WNI atau keturunan WNI yang ingin kembali ke Indonesia bukan untuk mengejar privilese, melainkan untuk hidup, bekerja, dan berkontribusi secara wajar.
Kritik ini mengungkap persoalan tersebut, bahwa GCI lebih dekat pada logika residensi daripada logika kewargaan. Ia mengatur soal tinggal, bukan soal menjadi bagian penuh dari sebuah negara. Dalam perspektif ini, GCI dikhawatirkan hanya menjadi solusi pintas, tapi untuk jangka panjang mengandung resiko, sebab belum tentu menjawab kebutuhan identitas, rasa memiliki, dan kepastian.
Di titik inilah muncul kecurigaan bahwa GCI hanyalah cara negara menunda perdebatan yang lebih penting, meski sensitif, yaitu perlunya diberlakukan kewargaan ganda.
GCI sebagai Awal Percakapan
Terlepas dari kritik yang ada, menilai GCI semata sebagai kebijakan gagal juga tidak sepenuhnya adil. GCI dapat dipahami sebagai tahap awal, semacam laboratorium kebijakan kewargaan. Melalui kebijakan ini, negara dapat mengamati dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari pengakuan keterikatan non-kewargaan secara lebih sistematis.
Yang menjadi kunci adalah bagaimana pemerintah memposisikan GCI ke depan. Jika GCI dianggap sebagai solusi final, maka risiko stagnasi kebijakan sangat besar. Namun, jika ia diperlakukan sebagai batu loncatan menuju reformasi kewargaan yang lebih matang, maka GCI justru memiliki nilai strategis.
Evaluasi berkala, penyederhanaan prosedur, transparansi biaya, serta dialog terbuka dengan diaspora dan masyarakat sipil menjadi prasyarat mutlak. Selain itu, negara juga perlu berterusterang mengakui bahwa konsep kewarganegaraan tidak lagi bisa sepenuhnya disandarkan pada asumsi loyalitas tunggal yang statis.
Di banyak negara, kewarganegaraan ganda tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber daya strategis. Diaspora dilihat sebagai aset diplomasi, ekonomi, dan budaya. Indonesia tentu memiliki konteks historis dan politik yang berbeda, tetapi perbedaan konteks tidak seharusnya menutup kemungkinan belajar dan beradaptasi.
Meski debatable GCI ini menjadi refleksi atas dilema klasik negara-bangsa di abad ke-21, tentang bagaimana menjaga kedaulatan tanpa menutup diri, dan bagaimana merawat identitas nasional tanpa menolak realitas global. Kebijakan ini tentu belum sempurna, bahkan masih menyisakan banyak pertanyaan konseptual. Namun, ia menandai satu hal penting, bahwa negara mulai terbuka dan bergerak.
Karenanya, GCI seharusnya dipahami bukan sebagai akhir dari perdebatan kewarganegaraan, melainkan sebagai awal percakapan nasional yang lebih dewasa tentang siapa yang kita akui sebagai bagian dari Indonesia. Jika percakapan ini dijalankan dengan keterbukaan intelektual dan kedewasaan politik, maka GCI bisa menjadi tonggak penting dalam evolusi kebijakan kewargaan Indonesia.