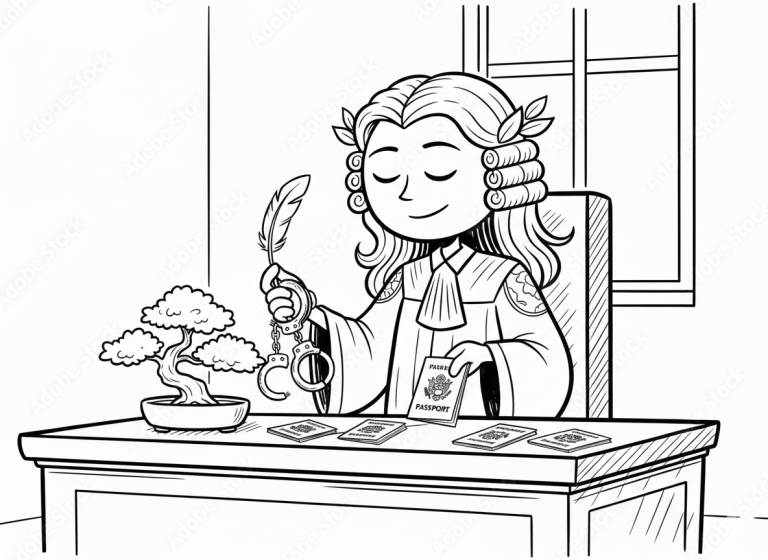Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan Pondok PesaSelntren Al Khoziny di Sidoarjo yang merenggut nyawa 63 santri. Kedua, kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia di Jakarta yang menewaskan 22 orang. Keduanya bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan tragedi struktural yang mengungkap celah dalam tata kelola keselamatan publik. Dan, lebih jauh, kelemahan dalam praktik kewarganegaraan substantif di Indonesia. Artikel ini berupaya meneropong relasi kewarganegaraan dan agama melalui sosok Ali Sadikin, dan kedua tragedi tersebut di atas.
Yang menarik bukan hanya skala korban, melainkan respons negara yang kontras terhadap kedua insiden tersebut. Dalam kasus Terra Drone, negara bertindak cepat: Direktur Utama perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal kelalaian, dan ditahan dalam waktu 48 jam pasca-tragedi. Polisi secara eksplisit mengungkap enam bentuk kelalaian manajemen, mulai dari tidak adanya SOP penyimpanan baterai hingga ketiadaan jalur evakuasi. Tentu kerja cepat kepolisian ini patut diapresiasi.
Namun selain apresiasi yang juga tampak dari lini masa media sosial. Netizen sekaligus mempertanyakan dan membandingkannya dengan tragedi robohnya Pesantren Al Khoziny. Dalam kasus Pesantren Al Khoziny, respons negara justru berfokus pada rehabilitasi simbolik. Pada 11 Desember 2025, pemerintah sudah menyatakan akan membantu membangun kembali melalui APBN. Tak tanggung-tanggung, negara mengalokasikan dana sebesar Rp125,3 miliar. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada pengumuman resmi tentang penyelidikan terhadap pengelola pesantren. Meskipun laporan awal menyebut bahwa santri terlibat langsung dalam pekerjaan konstruksi, termasuk pengecoran lantai atas. Suatu praktik yang rentan terhadap pelanggaran standar keselamatan kerja dan perlindungan anak.
Ali Sadikin dan Netralitas Ruang Publik
Kontras ini mengundang kita untuk menoleh ke masa lalu—khususnya pada sosok Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta (1966–1977). Sosok yang dikenal karena upayanya memisahkan kebijakan publik dari tekanan moral keagamaan. Contohnya, ketika dikritik ulama atas kebijakan pajak perjudian untuk membiayai pembangunan Jakarta. Ia dengan tegas meminta agar mereka tidak usah melewati jalan yang dibangun dari pajak judi tersebut. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa ruang publik harus dikelola berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Bukan otoritas moral kelompok tertentu.
Ali Sadikin bukanlah figur liberal dalam pengertian kontemporer. Namun, ia memahami bahwa keadilan administratif dan akuntabilitas struktural adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, negara tidak boleh tunduk pada logika simpati selektif—apalagi jika hal itu mengorbankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum semua warga negara.
Ketika Simpati Menggantikan Akuntabilitas
Dalam tragedi Al Khoziny, negara tampak terjebak dalam logika yang keliru, yang justru berpotensi melahirkan impunitas berbasis afiliasi keagamaan. Bantuan APBN senilai ratusan miliar rupiah memang mencerminkan solidaritas negara. Tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan proses hukum independen yang menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian struktural yang menewaskan puluhan anak?
Pertanyaan ini bukan serangan terhadap institusi pesantren—justru sebaliknya. Menganggap pesantren sebagai “ruang suci” yang kebal dari audit keselamatan akan mereduksi hak santri sebagai warga negara penuh. Santri Al Khoziny dan para pekerja di kantor Terra Drone memiliki posisi yang sama. Lini media sosial pun ramai membahas hal ini. Bahkan tidak sedikit netizen yang berkomentar bahwa ini bukan soal bias agama, tapi bias elektoral. Bukan rahasia lagi bahwa pesantren selama ini merupakan salah satu lumbung suara yang menggiurkan bagi para politisi.
Pertanyaan tentang Konsistensi Penegakan Hukum
Krisis yang muncul dari dua tragedi ini bukanlah krisis agama atau bisnis, melainkan krisis konsistensi negara dalam menegakkan prinsip kewarganegaraan. Ketika kelalaian di sektor korporat ditanggapi dengan penegakan hukum, sementara kelalaian di institusi keagamaan ditanggapi dengan bantuan tanpa pertanggungjawaban, maka yang terjadi adalah fragmentasi hak warga negara berdasarkan konteks sosial tempat mereka berada.
Kewarganegaraan yang adil menuntut: Kesetaraan nyawa: tidak ada nyawa yang lebih “terlindungi” atau lebih “terlupakan” karena afiliasi institusionalnya; Pemisahan tegas antara bantuan kemanusiaan dan proses hukum; Pengakuan bahwa institusi keagamaan tetap tunduk pada standar keselamatan publik dan perlindungan anak.
Ali Sadikin mungkin hidup di era yang berbeda, tetapi pesannya relevan: negara harus hadir sebagai penjaga prinsip, bukan sebagai penyalur simpati yang diskriminatif. Dalam mengenang 85 jiwa yang hilang dari dua tragedi ini, satu tuntutan moral mendasar muncul: agama ataupun modal tidak boleh menjadi perisai bagi penegakan hukum. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali. Bukankah demikian bunyi salah satu pasal UUD Negara Republik Indonesia?