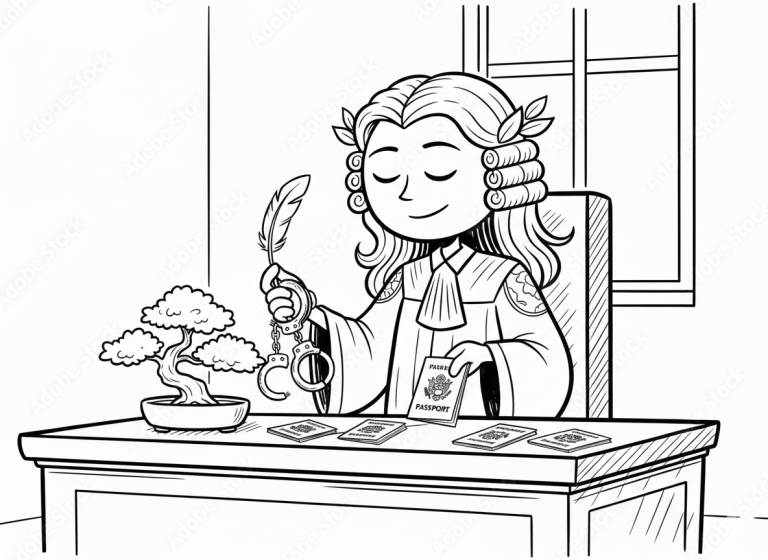Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu pindah ke Australia pada 2013, lalu menjadi warga negara setempat demi mengejar mimpi olahraganya. Kini, ia telah tampil di Olimpiade, Commonwealth Games, dan turnamen internasional lainnya—semua di bawah bendera Kanguru.
Namun, ketika pemerintah Indonesia mengumumkan Kewarganegaraan Global Indonesia (GCI), Setyana merasa ada pintu yang perlahan terbuka. Bukan untuk kembali jadi WNI—ia tak ingin melepas kewarganegaraan barunya—tapi untuk pulang tanpa hambatan birokrasi, melatih anak-anak di kampung halamannya, atau sekadar menjenguk keluarga di Sulawesi Utara tanpa khawatir visa habis masa berlaku.
“Indonesia selalu menjadi rumah saya,” katanya lirih. “Tapi selama ini, setiap kali ada tawaran kerja di sana, saya terkendala izin tinggal. Saya sudah bukan WNI lagi.”
Saat Nostalgia Bertemu Kebijakan
GCI adalah skema visa khusus yang diluncurkan Kementerian Hukum dan HAM (melalui Direktorat Jenderal Imigrasi) sebagai upaya merangkul diaspora. Dengan GCI, mantan WNI, keturunan hingga dua generasi, dan pasangan WNI bisa tinggal menetap di Indonesia tanpa batas waktu, bekerja, berbisnis, dan bolak-balik bebas—semua tanpa harus melepas kewarganegaraan asal.
Di atas kertas, ini terdengar seperti jawaban atas permintaan lama diaspora: pengakuan tanpa syarat penuh menjadi WNI, tapi juga tanpa dikucilkan. Namun, ketika kebijakan turun ke lapangan, kisahnya jadi lebih rumit.
Antara Harapan dan Realitas yang Mahal
Tuti Poeppelmeyer, perempuan asal Jakarta yang kini tinggal di Bremen, Jerman, menyambut GCI dengan hati berdebar. Ia sudah 13 tahun menetap di Eropa, menikah dengan warga negara asing, dan punya putri berusia 11 tahun. Tapi ia masih memegang paspor Indonesia—bukan karena cinta pada cap imigrasi, melainkan karena warisan tanah dari orang tuanya.
Di Indonesia, WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Jika seorang WNI mewariskan properti ke anak yang sudah jadi WNA, tanah itu harus dijual dalam waktu satu tahun—atau statusnya otomatis turun menjadi “hak pakai”, yang berlaku maksimal 30 tahun.
“Satu-satunya alasan saya belum ganti kewarganegaraan adalah karena tanah itu,” kata Tuti. “Kalau GCI benar-benar memungkinkan saya tetap memegang properti itu meski jadi WNA… saya akan melepas paspor Indonesia dengan lega.”
Tapi harapan itu kini menggantung. Kementerian Imigrasi mengonfirmasi: hak kepemilikan tanah dan properti belum diatur dalam skema GCI. Semua masih tunduk pada undang-undang agraria yang berlaku—dan undang-undang itu tak mudah berubah.
Merasa Tidak Disambut
Tidak semua menyambut GCI dengan optimisme. Di Bali, Nuning Hallett—aktivis diaspora dan ibu tiga anak dari pernikahan campuran—menyebut skema ini “mengecewakan”.
“Jangan begini caranya,” katanya tegas. “Kita merasa seperti dipalak, bukannya disambut.”
Nuning membandingkan GCI dengan Overseas Citizenship of India (OCI), skema serupa yang diadopsi India sejak 2005. OCI memungkinkan diaspora India memiliki rekening bank, beli apartemen, bepergian bebas, dan bahkan membuka usaha—semua hanya dengan biaya sekitar US$300.
Sementara itu, GCI meminta komitmen finansial hingga US$25.000 (sekitar Rp416 juta) bagi keturunan generasi kedua, ditambah biaya administrasi Rp34,8 juta. Dan itu bukan investasi yang menghasilkan imbal—hanya “bukti komitmen”, seperti kata pejabat imigrasi.
“Kalau India membuka pintu dengan pelukan, kita membukanya dengan tagihan,” sindir Nuning.
Ia juga menyoroti masalah hukum mendasar: GCI hanya diatur dalam Peraturan Menteri, bukan undang-undang. Artinya, tidak mungkin GCI memberikan hak yang bertentangan dengan UU seperti UU Agraria, UU Penanaman Modal, atau UU Kewarganegaraan.
“Mana mungkin Permen bisa mengalahkan UU? Ini seperti memberi kunci emas ke gembok yang bahannya beton.”
Dwi Kewarganegaraan: Tabu yang Tak Kunjung Usai
Bagi banyak diaspora, akar persoalan bukan pada visa atau izin tinggal—tapi pada asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia sejak 1945.
Berbeda dari negara seperti AS, Kanada, atau Prancis yang mengakui dwi kewarganegaraan, Indonesia memaksa setiap WNI yang mengambil kewarganegaraan asing untuk melepas statusnya sebagai WNI—dan kehilangan hak-hak sipil, termasuk warisan, akses ke layanan publik, bahkan ikatan hukum dengan tanah kelahirannya.
GCI memang hadir sebagai “jalan tengah”. Tapi bagi banyak orang, ini terasa seperti memberi perban pada luka yang butuh operasi.
Selanjutnya Apa?
Pemerintah bersikeras bahwa GCI masih dalam tahap penyempurnaan. Abdullah Rasyid, Staf Ahli Menteri Imigrasi, mengatakan bahwa GCI akan terus dikembangkan agar “menyamai bahkan melampaui kualitas OCI India”. Peluncuran resminya dijadwalkan pada 26 Januari 2026.
Namun, komunitas diaspora—termasuk akademisi, aktivis, dan organisasi seperti Jaringan Diaspora Indonesia—justru mendorong revisi menyeluruh UU Kewarganegaraan. Bagi mereka, solusi jangka panjang bukan terletak pada skema imigrasi, tapi pada pengakuan konstitusional terhadap ikatan emosional dan historis yang tak pernah putus, meski paspor biru telah berganti warna.
Rumah Tak Hanya Soal Alamat
Bagi Setyana, Tuti, Nuning, dan jutaan diaspora lainnya, Indonesia bukan sekadar negara—tapi kenangan masa kecil, aroma dapur ibu, logat kampung, dan rasa rindu yang tak berujung. Mereka tak meminta kembali jadi WNI secara hukum, tapi ingin diperlakukan seperti bagian dari keluarga, bukan seperti investor asing yang harus “membayar untuk pulang”.
GCI mungkin langkah pertama. Tapi agar langkah itu bermakna, ia harus dibangun di atas empati, bukan ekonomi. Karena rumah—sejati—tak diukur dengan deposito, melainkan dengan hati yang tetap terbuka.@esa
Sumber: Selena Souisa, ABC.Net