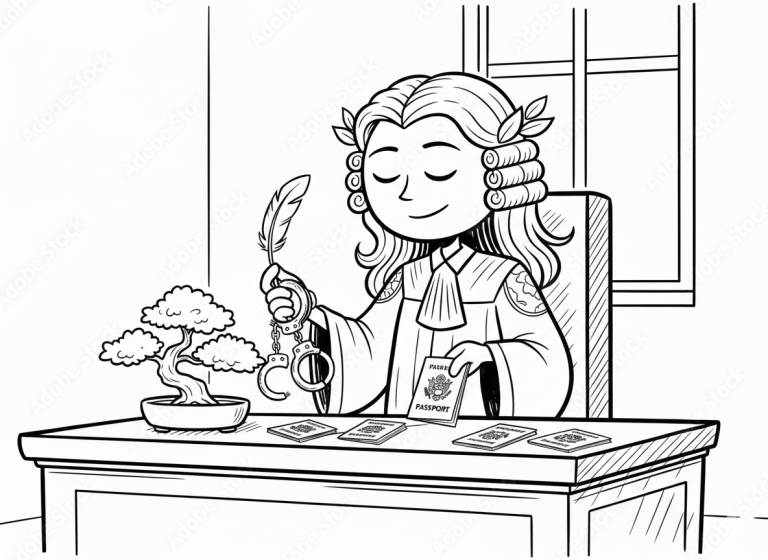Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ?
Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka perlu diadakan kritik terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 (Perpres Nomor 10 tahun 1959). Yang diterbitkan pada hari Senin Kliwon, tanggal 16 Nopember 1959. Perpres Nomor 10 tahun 1959 itu bagaikan ‘malapetaka’ bagi peranakan Tionghoa. Jika kita menggunakan kebenaran komparatif Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 tentang Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 1959 sebagai pelaksanaan perjanjian bilateral Pemerintah RI-RRC.
Dengan pendekatan komparatif ini akan terlihat jelas adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah. Baik terhadap kesepakatan bilateral Pemerintah RI-RRC maupun penegakan hukum. Atau dengan pendekatan kajian lain telah terjadi penyimpangan dari kesepakatan Pemerintah RI-RRC dalam penegakan hukum.
Mengenai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959. Antara lain berisi peraturan tentang larangan bagi orang asing untuk melakukan kegiatan perdagangan secara formal, terutama pada tingkat pedesaan/kecamatan.
Sekalipun dalam ketentuan ada jaminan tidak akan terjadi kericuhan. Namun dalam pelaksanaannya kemudian, pemerintah tidak mampu menjamin ketertiban. Hiruk pikuk dan kesemrawutan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 10 tahun 1959. Menyebabkan ± 140.000 kepala keluarga warga etnik Tionghoa telah tergusur dari pemukimannya di kecamatan-kecamatan atau desa-desa. Mereka dipaksa mengungsi ke daerah Tingkat II Kabupaten.
Pelaksanaan Perpres Nomor 10 tahun 1959. Bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 10 tahun 1959 itu sendiri yang berbunyi:
“Penampungan tenaga-tenaga termaksud pada ajat (1) pasal ini dilaksanakan setjara bidjaksana dengan memperhatikan segi-segi perikemanusiaan. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut pada ajat-ajat jang terdahulu. Pasal ini harus dihindarkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan jang dapat mengeruhkan suasana didaerah-daerah jang bersangkutan”.
Proses pemulangan orang-orang yang tergusur ketika itu diperkirakan hanya mencapai ± 40.000 kepala keluarga. Tetapi karena pemerintah RRC tidak lagi mengirim kapal-kapal pengangkut ke Indonesia. Maka pengangkutan warga Tionghoa itu terhenti, akibatnya masih terdapat kira-kira 100.000 orang lebih tetap berada di Indonesia. Tanpa ada kejelasan status kewarganegaraan mereka.
Dari sisi peraturan, berbagai kebijakan keimigrasian maupun kehakiman ‘menyudutkan’ mereka. Orang-orang ini telah dianggap menyerahkan identitas ke-asing-annya dan diberikan exit permit only (EPO). Inilah penyebab awal dari permasalahan yang dapat disebut sebagai ‘malapetaka’. Karena tidak ada yang bertanggung-jawab mengenai proses pengurusan bagi mereka untuk kembali ke tanah leluhur. Dari aspek dokumen keimigrasian yang dimiliki orang-orang ini hanya EPO.
Pendekatan komparatif ini akan dicoba dengan melihat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959. Sebagai peraturan pelaksanaan perjanjian Dwi-Kewarganegaraan yang menetapkan berlakunya perjanjian mulai hari Rabu Kliwon, tanggal 20 Januari 1960.
Dilihat secara kronologis juga ada hal yang patut disimak. Mengingat kira-kira 2 bulan menjelang mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian bilateral Pemerintah RI-RRC, di lapangan terjadi tindakan “pengusiran” terhadap etnik Tionghoa. Dari daerah kecamatan dan desa dengan alasan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959. Tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran. Yang bersifat asing diluar ibukota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan.
Maka dapat dipahami apabila terjadi kepanikan di kalangan masyarakat etnik Tionghoa. Yang dengan harap-harap cemas menantikan pelaksanaan perjanjian dwi-kewarganegaraan. Padahal isi perjanjian dwi kewarganegaraan itu belum dipahami benar atau sosialisasinya belum jelas, tetapi telah terjadi pengusiran di banyak tempat.
Berbicara tentang siapa Warga Negara Asing (WNA). Tidak bisa hanya dengan melihat hukum positif yang berlaku saat itu – Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 – . Tetapi harus merunut kembali pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Yang bermuara pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947. Memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 1948. Tentang memperpanjang lagi pengajuan pernyataan Kewarganegaraan Negara Indonesia.
Di dalam Pasal 1 ayat (a) dan ayat (b) mengenai siapa yang disebut warga negara Indonesia secara jelas dikatakan bahwa:
(a). orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
(b). orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas (ayat a) akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu. Yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud. Yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut. Paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun. Atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain;
Dengan demikian tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 ditemukan orang Indonesia (peranakan Tionghoa) yang terkena ‘pengusiran’ tanpa memperhatikan proses sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat minimnya kemampuan administrasi birokrasi memperoleh data menyangkut kependudukan dan kewarganegaraan atau apakah memang ada unsur kesengajaan? Khusus untuk etnis Tionghoa, Pemerintah Republik Indonesia terikat pada perjanjian bilateral Pemerintah RI-RRC yang belum dilaksanakan untuk menentukan Siapa Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.
Seperti telah dijelaskan diatas, fakta yang terjadi ketika itu adalah orang peranakan Tionghoa yang berusaha dagang eceran di daerah kecamatan atau desa menjadi sasaran pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut.
Sementara itu, terbitnya Perpres Nomor 10 tahun 1959 ini juga menyengsarakan rakyat Indonesia pada umumnya, terutama yang tinggal di desa-desa atau yang tinggal di pedalaman, karena mereka tidak dapat menjual hasil bumi atau panennya kepada pedagang yang kebanyakan etnis tionghoa.
Dari kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa secara transparan tindakan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa telah dilakukan oleh negara. Karena yang seharusnya menjadi sasaran Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 tersebut adalah orang asing atau warga negara asing.
| Dapat dikatakan bahwa tindakan diskriminasi dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 apabila dikaji dari peraturan perundangan, sekurang-kurangnya bertentangan dengan surat Perdana Menteri Dewan Negara RRC kepada Perdana Menteri RI tanggal 3 Juni 1955 yang bersepakat antara lain :
“Pemerintah RRC dan Pemerintah RI menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan RI dan RRC terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai dwi-kewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah RI, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya RRC. Orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan”. |
Dari sikap yang dituangkan dalam Surat Perdana Menteri Dewan Negara RRC ini sesungguhnya pihak asing menghormati segala sesuatu yang telah dicapai oleh Pemerintah RI sebagai negara berdaulat, tetapi dalam kenyataannya hal itu tidak dihargai oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Penghormatan terhadap negara asing itu diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 tanggal 26 Mei 1959 yang menerangkan bahwa wewenang menentukan orang peranakan Tionghoa adalah Warga Negara Indonesia Tunggal ialah Wewenang Mutlak Pemerintah Indonesia.
|
Wewenang mutlak yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959, sebagai berikut : “Karena wewenang yang oleh perjanjian diberikan kepada Pemerintah RI adalah wewenang mutlak dan karena orang-orang termaksud, setelah ditentukan oleh pemerintah RI, menjadi warganegara (RI) tunggal, maka orang-orang itu tidak saja tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian, melainkan orang-orang itu juga tidak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian itu. Dengan lain perkataan, orang-orang itu tidak boleh menolak anggapan Pemerintah RI, bahwa mereka warganegara RI tunggal; mereka tidak boleh memilih untuk dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dwi-warganegara. Dalam menentukan orang-orang yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RRC-nya itu Pemerintah RI tidak hanya harus melihat kepada kedudukan sosial atau politik orang-orang itu, melainkan juga harus melihat kepada perundang-undangannya sendiri atau mengingat azas-azas yang sudah lazim dilakukan”. |
Dengan demikian, sejak berdirinya Negara Kesatuan RI cukup jelas dan transparan siapa warga negara RI. Negara dan pemerintah seperti RRC dengan tegas menghormati Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, oleh karena itu kewenangan menentukan siapa warga negara RI diberikan mutlak kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Dengan memperhatikan penjelasan yang tertera dalam perundangan di atas, menjadi sangat jelas bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan berbagai aspek legal, bahkan cenderung tidak menghormati atau menghargai ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah sendiri.
Seperti sudah diuraikan di atas, ketentuan ini mengakibatkan status hukum kewarganegaraan bagi peranakan Tionghoa semakin tidak jelas. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 ini juga menginterupsi proses persiapan pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan, karena status asing atau bukan asing bagi orang-orang Tionghoa yang menjadi korban peraturan presiden tersebut, sebenarnya belum dapat ditetapkan sebelum dilaksanakannya masa opsi perjanjian dwi kewarganegaraan antara tahun 1960-1962. Apalagi sebenarnya hal itu telah ditetapkan di dalam perjanjian RI-RRC, bahwa sebelum perjanjian dilaksanakan (dua tahun masa opsi diberlakukan), status orang-orang yang masuk dalam objek perjanjian adalah status quo. Sehingga Peraturan Presiden 10 tahun 1959 ini merupakan kebijakan yang diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa.
Akibat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 tersebut, tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga sarat dengan persoalan politik dan hukum.
Dalam bidang ekonomi misalnya, terjadi pengambilalihan usaha dari warga keturunan Tionghoa oleh pribumi melalui koperasi. Pelaksananya selain Pamong Praja juga melibatkan Militer – Bintara Onder District Militer (BODM) – setara dengan Koramil;
Di bidang politik, terjadi gerakan rasialis anti-Tionghoa, sementara keturunan etnis lain tidak menjadi sasaran;
Dalam bidang hukum menyebabkan: tidak adanya kepastian hukum bagi etnis Tionghoa, sekalipun ada perjanjian internasional secara bilateral antara pemerintah RI dengan RRC; warga masyarakat yang tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki dokumen, hanya diberikan dokumen keimigrasian exit permit;
Pada perkembangan kemudian, setelah bertahun-tahun, dokumen exit permit yang mereka miliki diganti dengan dokumen keimigrasian atau mereka diberikan status asing, seperti Surat Pendaftaran (SP), Surat Tanda Pelaporan (STP), Pendaftaran Orang Asing (POA), Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS), dan lain-lain;
Selain itu, hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia – RRC ketika itu juga sempat memanas. Kantor Berita Antara, Kamis Kliwon, 19 Mei 1960 menurunkan berita bahwa Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri meminta kepada Kedutaan Besar RRC agar dua Konsul RRC ditarik dari posnya, yaitu Liu Ching Yu, Konsul di Medan dan Chiang Yen, Konsul di Banjarmasin. Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa hanya sedikit etnis Tionghoa yang berhasil berangkat ke RRC, sisanya yang diduga berjumlah sekitar seratusan ribu kepala keluarga menjadi pemukim di Indonesia sampai hari ini. @adji
https://www.yayasan-iki.or.id/berita/12/06/2023/tokoh-tionghoa-dan-masalah-kewarganegaraan/