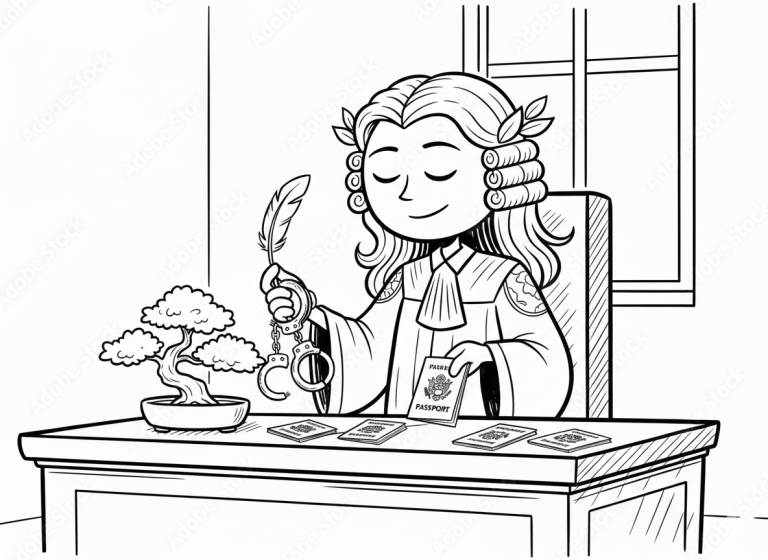Diskriminasi ras dan etnis bukanlah masalah baru. Sejak lama, ia menjadi tantangan yang terus hadir dalam sejarah umat manusia. Upaya melakukan penghapusan diskriminasi di berbagai negara pun telah hadir menjawab tantangan tersebut. Meski demikian, bahkan di negara-negara maju pun, diskriminasi masih menjadi kenyataan pahit. Amerika Serikat sering disebut sebagai contoh paling nyata: meski gerakan hak-hak sipil sudah berlangsung sejak 1960-an, rasisme tetap berakar kuat dalam sistem sosial. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, retorika politik yang tajam membelah masyarakat semakin memperburuk relasi antar kelompok. Komunitas imigran, Asia-Amerika, dan masyarakat kulit hitam kerap menjadi sasaran ujaran kebencian maupun kebijakan eksklusif.
Kasus George Floyd pada 2020 yang menimbulkan gelombang protes global memperlihatkan betapa diskriminasi berbasis ras masih menjadi luka mendalam. Di Eropa, menguatnya politik populis kanan melahirkan kebijakan yang semakin membatasi migran dan minoritas, sementara di Australia, diskriminasi terhadap masyarakat Aborigin tetap menjadi persoalan serius.
Bagaimana dengan Indonesia?
Fenomena global ini menunjukkan bahwa diskriminasi ras dan etnis tidak hanya melekat pada negara berkembang atau pascakolonial, melainkan merupakan masalah universal. Indonesia pun tidak luput dari persoalan yang sama. Meski nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia semakin dikedepankan, diskriminasi tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kebijakan maupun dalam interaksi sosial. Bentuk diskriminasi bisa terlihat jelas, seperti ujaran kebencian dan kekerasan berbasis identitas, namun juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus, misalnya pelayanan publik yang berbeda, stereotip, atau prasangka yang diwariskan turun-temurun. Meskipun sudah ada upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sejak era reformasi.
Diskriminasi di Indonesia sangat kentara dalam relasi dengan dua kelompok etnis: masyarakat Tionghoa dan masyarakat Papua misalnya. Keduanya sama-sama mengalami sejarah panjang perlakuan tidak adil. Sejak masa kolonial, etnis Tionghoa sering dipandang sebagai “asing” meski sudah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan budaya Nusantara. Pada masa Orde Baru, diskriminasi dilembagakan dalam bentuk larangan penggunaan bahasa dan simbol budaya Tionghoa, pembatasan dalam pendidikan dan birokrasi, hingga kewajiban asimilasi yang meniadakan identitas etnis mereka. Walaupun setelah Reformasi banyak kebijakan diskriminatif dicabut, stigma bahwa orang Tionghoa bukan bagian penuh dari bangsa Indonesia masih kerap muncul, terutama di media sosial atau dalam retorika politik tertentu.
Bagi masyarakat Papua, diskriminasi memiliki wajah berbeda. Warna kulit, ciri fisik, dan stereotip yang dilekatkan membuat orang Papua sering dianggap “berbeda” atau “terbelakang”. Diskriminasi yang mereka alami tidak hanya berupa prasangka sosial, tetapi juga keterpinggiran dalam pembangunan. Akses pendidikan dan layanan kesehatan masih jauh tertinggal, sementara kekerasan dan sikap represif dari aparat kerap memperburuk perasaan keterasingan. Insiden ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019, yang kemudian memicu kerusuhan besar di Papua, memperlihatkan bahwa diskriminasi verbal dapat berujung pada konflik sosial berskala luas.
Sejarah Diskriminasi
Sejarah diskriminasi ini tidak bisa dilepaskan dari akar kolonialisme. Pada masa kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi sosial berdasarkan ras, dengan orang Eropa menempati posisi teratas, Timur Asing di tengah, dan pribumi di bawah. Pola hierarki ini diwariskan dalam bentuk prasangka yang hingga kini masih membekas. Diskriminasi kemudian terinternalisasi dalam struktur kekuasaan, kebijakan, dan interaksi sosial sehari-hari.
Bentuk diskriminasi hari ini dapat ditemukan di berbagai bidang. Dalam pendidikan, anak-anak dari kelompok tertentu masih menghadapi akses yang lebih terbatas, fasilitas yang tidak merata, hingga kurikulum yang kurang mencerminkan keragaman budaya. Dalam dunia kerja, diskriminasi tercermin dari kesenjangan upah, sulitnya kelompok minoritas memperoleh posisi strategis, serta prasangka terhadap kemampuan mereka. Di sektor kesehatan, layanan yang tidak setara menghasilkan tingkat kematian yang lebih tinggi di kalangan minoritas, termasuk masyarakat adat di daerah terpencil. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi kerap hadir dalam bentuk ejekan, stereotip, hingga perlakuan tidak adil oleh aparat penegak hukum.
Mengapa diskriminasi masih terus terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah stereotip dan prasangka yang dilekatkan pada kelompok tertentu. Stereotip membuat orang dipandang bukan sebagai individu, melainkan sebagai representasi dari kelompoknya. Ketakutan terhadap perbedaan juga memainkan peran penting. Ketika mayoritas merasa identitasnya terancam oleh keberadaan kelompok lain, sikap intoleran sering muncul. Selain itu, struktur kekuasaan yang timpang ikut melanggengkan diskriminasi. Sejarah panjang penindasan menciptakan ketidaksetaraan yang sulit dihapus meski undang-undang sudah berubah.
Indonesia Sudah Punya UU dan SNP Penghapusan Diskriminasi
Dampak diskriminasi tidak bisa dianggap remeh. Secara sosial, diskriminasi memperlebar jarak antarkelompok dan memicu polarisasi. Secara ekonomi, diskriminasi menghambat potensi individu atau kelompok untuk berkembang, menurunkan produktivitas, dan memperbesar ketimpangan. Dari sisi psikologis, diskriminasi menimbulkan stres, depresi, dan gangguan mental lainnya yang melemahkan kepercayaan diri korban dalam jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena melarang diskriminasi berbasis ras dan etnis serta memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut keadilan. Namun, implementasinya masih jauh dari memadai. Banyak kasus diskriminasi berakhir tanpa penyelesaian, atau hanya diproses secara administratif tanpa menyentuh akar masalah.
Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM
Sebagai upaya memperkuat kerangka hukum tersebut, Komnas HAM menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). SNP ini menegaskan bahwa diskriminasi rasial dan etnis adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ia memberikan panduan interpretatif agar negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil memiliki acuan yang sama dalam menilai praktik diskriminasi. Dengan SNP ini, Komnas HAM tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai rujukan resmi dalam menilai kebijakan dan tindakan diskriminatif.
Namun SNP 2020 juga memiliki keterbatasan. Ia bersifat non-mengikat, sehingga tidak otomatis wajib diikuti lembaga negara. Sosialisasinya pun masih terbatas, terutama di daerah, padahal diskriminasi banyak terjadi di level pelayanan publik lokal. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan memberi rekomendasi, bukan menjatuhkan sanksi. Akibatnya, banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Selain itu, SNP belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Padahal diskriminasi sering muncul dalam konteks lokal, baik terhadap warga Papua, Tionghoa, maupun kelompok adat lainnya.
Contoh kasus pasca-2008 memperlihatkan bahwa tantangan masih besar. Ujaran kebencian berbasis etnis Tionghoa masih marak di media sosial. Diskriminasi dalam perekrutan kerja masih dirasakan masyarakat Papua, yang kerap dianggap kurang cakap, atau warga Tionghoa yang dicurigai memiliki loyalitas ganda. Dalam layanan publik, warga Papua sering menghadapi birokrasi yang lambat dan diskriminatif. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa diskriminasi bukan sekadar isu masa lalu, melainkan realitas yang terus hadir.
Apa yang bisa dilakukan?
Pendidikan dan kesadaran publik menjadi langkah penting. Toleransi dan empati harus ditanamkan sejak dini, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, memastikan UU No. 40/2008 dijalankan dan SNP 2020 dijadikan acuan dalam evaluasi kebijakan. Komnas HAM perlu diperkuat agar rekomendasinya memiliki daya ikat yang lebih kuat. Pemerintah daerah juga harus mulai mengintegrasikan SNP ke dalam program pembangunan dan pelayanan publik. Di luar itu, gerakan masyarakat sipil tetap menjadi motor penting untuk membongkar praktik diskriminasi, menekan perubahan kebijakan, sekaligus menumbuhkan solidaritas lintas identitas.
Diskriminasi rasial dan etnis adalah persoalan yang melekat dalam sejarah, tetapi bukan takdir. Indonesia memiliki instrumen hukum dan lembaga yang memadai, tinggal bagaimana memastikan implementasinya berjalan nyata. Kasus Tionghoa dan Papua memperlihatkan bahwa diskriminasi bisa menimbulkan luka sosial yang dalam jika tidak ditangani. Namun, dengan kesadaran kolektif, komitmen politik, dan keberanian masyarakat sipil, diskriminasi dapat dilawan.
Menghormati hak setiap individu tanpa memandang ras atau etnis bukan sekadar cita-cita moral, melainkan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan damai. Dalam dunia yang semakin majemuk, menghargai perbedaan adalah jalan menuju persatuan yang sejati.@esa