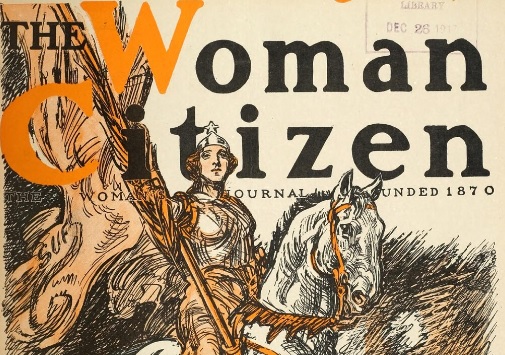Selama ini gender sering dipahami sebagai urusan identitas personal. Namun dalam praktik kenegaraan, gender adalah alat pengelolaan kekuasaan. Ia menentukan siapa yang dilindungi negara, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang dianggap dapat dikorbankan. Dalam satu tahun pertama pemerintahan Donald Trump periode kedua. Mekanisme ini bekerja secara terang-benderang. Kewarganegaraan perempuan dilemahkan.
Dari kebijakan imigrasi hingga penghapusan program keberagaman (DEI), dari kriminalisasi kehamilan hingga deregulasi lingkungan, negara secara sistematis mempersempit makna kewarganegaraan. Perlindungan negara tidak lagi universal, melainkan selektif. Perempuan, terutama yang miskin, rasial minoritas, queer, trans, dan penyandang disabilitas. Semakin sering ditempatkan di posisi warga negara bersyarat.
Isu-isu yang lazim disebut “isu perempuan” seperti aborsi, pengasuhan anak, atau biaya hidup sesungguhnya bukan isu sektoral. Ia menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang dianggap subjek politik utama dan bagaimana kewarganegaraan didefinisikan.
Gender dan Politik Kewarganegaraan Perempuan
Secara historis, kewarganegaraan di Amerika Serikat dibangun di atas norma patriarkal dan maskulinitas hegemonik kulit putih. Pemerintahan Trump tidak sekadar melanjutkan warisan ini, tetapi secara aktif berupaya memulihkannya. Gender dipahami sebagai kategori biologis biner dan hierarkis, yang kemudian dijadikan dasar untuk menata ulang kebijakan publik.
Tidak ada kebijakan yang netral gender. Ketika standar “warga negara ideal” ditentukan berdasarkan pengalaman laki-laki. Khususnya laki-laki kulit putih, cisgender, dan heteroseksual. Maka perempuan dan kelompok lain di luar standar tersebut diperlakukan sebagai pengecualian.
Hal ini terlihat jelas dalam cara negara mendefinisikan keamanan dan kekuatan. Penataan ulang institusi pertahanan, pelarangan tentara trans, serta penghapusan rekam jejak keberagaman dalam sejarah militer. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan penuh kembali dilekatkan pada maskulinitas militeristik.
Dalam logika ini, feminitas diasosiasikan dengan kerentanan. Maka melemahkan suatu kelompok dapat dilakukan dengan “memfeminisasi” mereka. Dengan membuat haknya dapat dinegosiasikan, keselamatannya bersyarat, dan keberadaannya tergantung pada belas kasihan negara.
Aborsi dan Otonomi Warga Negara
Aborsi kerap dipersempit sebagai isu moral atau agama. Namun dalam kajian kebijakan publik, khususnya di Amerika Serikat. Isu ini sesungguhnya berada di persimpangan antara kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, mobilitas sosial, dan kebebasan warga negara.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Berkontribusi pada meningkatnya partisipasi kerja, stabilitas pendapatan, serta keamanan hidup perempuan. Sebaliknya, pembatasan layanan tersebut dalam konteks Amerika. Justru berpotensi menciptakan rangkaian kerentanan. Seperti meningkatnya ketergantungan ekonomi, risiko kesehatan yang lebih tinggi, hingga keterlibatan perempuan dalam proses hukum yang seharusnya dapat dihindari.
Pengalaman ini penting dibaca bukan sebagai perdebatan moral. Melainkan sebagai pelajaran tentang bagaimana kebijakan negara dapat memperkuat atau melemahkan kewarganegaraan perempuan. Baik dalam posisi sosial dan ekonomi, hingga budaya dan politik.
Dalam sistem jaminan sosial yang bertumpu pada pekerjaan. Kehamilan yang mengganggu kerja dapat berarti kehilangan akses layanan kesehatan, utang medis, dan keterikatan pada relasi yang tidak aman. Dengan demikian, kebijakan reproduksi adalah kebijakan kewarganegaraan.
Perempuan dan Rumah
Pola serupa terlihat pada isu yang jarang dibaca sebagai isu perempuan, seperti perumahan. Bagi perempuan, rumah bukan sekadar soal harga dan lokasi, tetapi juga soal keselamatan dari kekerasan, stabilitas pengasuhan, dan kelangsungan hidup. Deregulasi kredit dan penghapusan perlindungan diskriminasi akan membuat akses perumahan bagi perempuan—terutama perempuan kulit hitam—semakin sulit.
Dalam berbagai sektor, negara memprivatisasi risiko, memindahkannya ke rumah tangga. Lalu mendorong perempuan untuk menyerap beban tersebut melalui kerja perawatan yang tidak dibayar. Dampaknya bersifat kumulatif: perempuan keluar dari pasar kerja dalam jumlah besar, sementara laki-laki justru masuk. “Fleksibilitas” kembali menjadi nama lain dari ketidakpastian.
(bersambung ke bagian 2/2)
Bacaan Lanjutan: