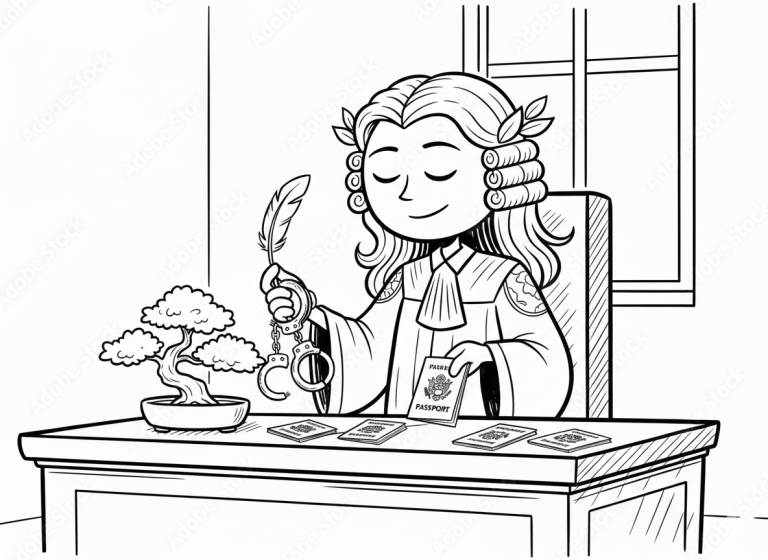Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam penanganan diskriminasi, yang merupakan bagian dari perlindungan HAM. Regulasi yang ada—seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dinilai memiliki cakupan yang masih terbatas. UU PDRE misalnya, hanya melindungi dari diskriminasi berbasis ras dan etnis. Sementara UU HAM, meski memberikan definisi diskriminasi yang lebih luas, tidak dilengkapi sanksi hukum yang memadai.
Padahal, praktik diskriminasi telah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga dalam layanan publik. Praktik pembedaan tersebut, dapat menyasar kelompok-kelompok yang tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum saat ini. Contohnya penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, kelompok gender non-biner, dan komunitas LGBTIQ+. Tanpa kerangka hukum yang komprehensif, korban diskriminasi kesulitan mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Merespon hal tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Konsorsium Crisis Response Mechanism dan UNAIDS telah mengambil langkah. Bersama-sama mereka telah menyusun Kajian Pendahuluan dan Kertas Advokasi untuk mendorong lahirnya Regulasi Penghapusan Diskriminasi yang utuh dan inklusif. Regulasi ini diusulkan sebagai single act—undang-undang tersendiri—yang mencakup:
Definisi diskriminasi dengan daftar karakteristik terbuka (open-ended list). Artinya ,tidak hanya mencakup dasar yang disebut secara eksplisit (seperti ras, agama, jenis kelamin), tetapi juga dapat mencakup “status lainnya”. Seperti orientasi seksual, identitas gender, kesehatan, usia, atau disabilitas, sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal HAM PBB.
Hasil Consultative Meeting
Bentuk-bentuk pelanggaran yang lebih luas, termasuk diskriminasi langsung, tidak langsung, struktural, dan institusional. Mekanisme penanganan dan sanksi yang proporsional, tidak hanya pidana, tetapi juga restitusi, rehabilitasi, dan pencegahan. Melalui serangkaian consultative meeting dengan berbagai Kementerian/Lembaga—seperti Bappenas, Kemenkumham (Ditjen HAM dan BPHN), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan—terungkap bahwa:
- Bappenas mendukung gagasan ini sebagai bagian dari agenda “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM” dalam RPJMN 2025–2029.
- Kemenkumham cenderung memasukkan substansi anti-diskriminasi ke dalam revisi UU HAM, meski belum siap mengusulkan undang-undang baru.
- Komnas HAM dan Komnas Perempuan menekankan pentingnya perlindungan yang lebih luas bagi kelompok rentan, serta perlunya pengarusutamaan prinsip non-diskriminasi di seluruh sektor.
Namun, tantangan politik tetap ada. Komnas Perempuan misalnya mengingatkan adanya potensi penolakan dari aktor konservatif. Sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari masyarakat sipil untuk memperkuat legitimasi usulan ini. IJRS merekomendasikan strategi advokasi yang komprehensif, meliputi:
- Penguatan advokasi kepada Ditjen HAM untuk mendorong lahirnya single act anti-diskriminasi.
- Perluasan jejaring masyarakat sipil guna memperkuat tekanan politik dan dukungan publik.
- Pengambilan peran sebagai leading sector dalam gerakan akar rumput.
- Penyusunan strategi alternatif, termasuk integrasi substansi anti-diskriminasi ke dalam revisi UU HAM atau pengusulan langsung melalui DPR.
Usulan regulasi ini bukan hanya soal hukum, tapi juga komitmen Indonesia terhadap prinsip HAM universal, keadilan sosial, dan keberagaman. Dengan regulasi yang kuat dan inklusif, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap warga negara—tanpa terkecuali—dilindungi dari segala bentuk diskriminasi.@esa