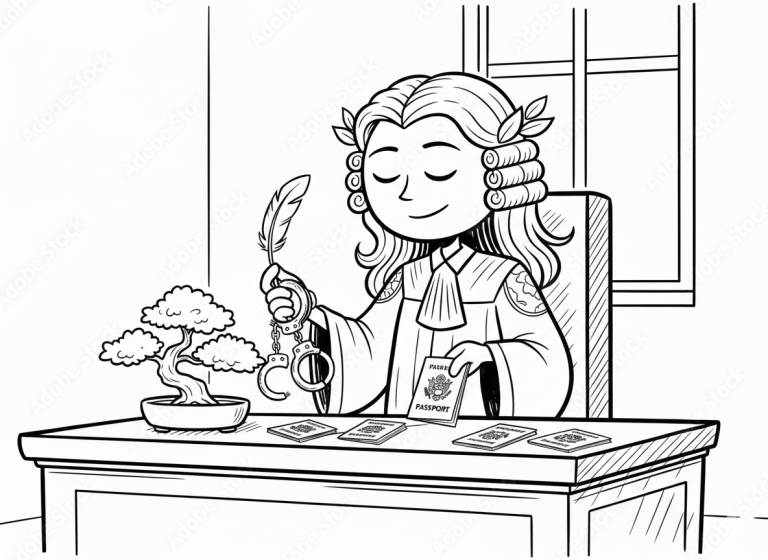Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan bagaimana menjaga persatuan di tengah keragaman etnis, bahasa, dan agama. Dua gagasan besar pernah mendominasi perdebatan politik dan sosial menyangkut Tionghoa dalam upaya menjawab tantangan ini. Pilihan yang tersedia adalah antara pendekatan integrasi dan belakangan hadir tawaran asimilasi.
Tionghoa dan Pilihan Integrasi
Pada dekade 1950-an, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) muncul dengan gagasan integrasi. Menurut paham ini, warga keturunan Tionghoa bisa tetap memelihara nama, tradisi, dan agamanya, asalkan menunjukkan kesetiaan pada bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam perjuangan nasional. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta, yang menegaskan bahwa meskipun secara hukum semua warga negara setara, realitas sosial masih dipenuhi prasangka sehingga integrasi membutuhkan waktu panjang.
Namun, posisi Baperki menjadi rumit ketika organisasi ini dituduh sebagai underbouw Partai Komunis Indonesia. Pasca-1965, organisasi ini dibubarkan dan gagasan integrasi kehilangan pijakan politik formal.
Asimilasi: Peleburan Identitas
Sebagai tandingan, pada 1963 dibentuk Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang mendorong gagasan asimilasi. Organisasi ini didukung juga oleh pihak militer, melengkapi lanskap politik pada masa itu yang penuh kontestasi ataraliran. Ada kelompok nasionalis, komunis, agama, dan militer. Menurut pandangan ini, kesatuan bangsa hanya mungkin tercapai jika kelompok minoritas melebur total ke dalam mayoritas. Identitas etnis dianggap penghalang, sehingga dorongan pergantian nama, perkawinan campur, hingga penghapusan simbol budaya menjadi agenda utama.
Negara memberi legitimasi penuh terhadap pendekatan ini, terutama di masa Orde Baru. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 menjadi tonggak penting, yang melarang perayaan adat, penggunaan bahasa, hingga ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik.
Konsekuensi Nyata Kebijakan Asimilasi bagi Tionghoa
Kebijakan ini berdampak luas, termasuk pada warga keturunan Tionghoa yang beragama Buddha. Hampir semua tempat ibadah yang di masyarakat dikenal sebagai kelenteng terpaksa menyesuaikan diri. Nama-nama berbahasa Mandarin diganti dengan istilah Sansekerta atau Indonesia. Misalnya, Kwan Im Teng di Banten menjadi Vihara Avalokitesvara, Kwan Im Miauw di Cirebon menjadi Wihara Dewi Welas Asih, dan kelenteng bersejarah Jin De Yuan di Jakarta diubah menjadi Vihara Dharma Bhakti.
Bukan hanya nama, tampilan arsitektur pun ditekan. Banyak kelenteng menutup patung naga pada pilar utama, bahkan ada yang memasang gapura berarsitektur lokal agar tidak terlalu menonjolkan nuansa Tionghoa. Lebih ironis lagi, praktik ritual turut terkena dampaknya: mantra-mantra Buddha Mahayana dalam bahasa Mandarin diganti dengan versi Sansekerta. Akibatnya, generasi tua mengalami kesulitan luar biasa karena tidak terbiasa, sementara generasi muda justru lebih fasih membaca mantra Sansekerta ketimbang Mandarin.
Celakanya, pada era reformasi malah muncul narasi umat Buddha merebut kelenteng milik Agama Konghucu. Padahal jelas bahwa gagasan untuk menjadikan Konghucu sebagai agama baru ada setelah 1900-an. Penggagasnya adalah Kangyou Wei, yang menyampaikan gagasan tersebut diantara proposal Reformasinya untuk penguasa Dinasti Qing. Sementara kelenteng-kelenteng di Indonesia sudah berdiri sejak era 1600-an. Gagasan Kangyou Wei tersebut gagal di negerinya sendiri. Oleh karena itu, hingga saat ini Konghucu tidak diakui diantara 5 agama yang diakui di Tiongkok, yaitu Buddha, Tao, Kristen, Katolik, dan Islam. Sedangkan di Indonesia pada masa Soekarno, Konghucu diakui sebagai agama. Kemudian tidak diakui di masa Orba, dan setelah era reformasi diakui kembali. Ketika diakui sebagai agama di masa Orde Lama, tempat ibadah Agama Konghucu disebut Lithang.
Pilihan asimilasi yang diikuti dengan penerapan formalnya, menunjukkan bagaimana asimilasi bukan sekadar wacana politik, tetapi hadir sebagai pengalaman sehari-hari warga yang membentuk identitas, bahkan menyentuh hingga di ruang spiritual. Termasuk juga menyasar bongpai atau nisan pada makam Tionghoa yang beraksara Mandarin. Semua harus diganti ke bahasa Indonesia.
Refleksi: Integrasi sebagai Jalan Tengah
Dari pengalaman sejarah ini terlihat jelas perbedaan kedua konsep. Integrasi berusaha merangkul keberagaman sebagai kekuatan, meski berjalan lambat. Asimilasi ingin menciptakan kesatuan cepat, tetapi dengan mengorbankan hak identitas dan ekspresi budaya.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya menawarkan jalan tengah khas Indonesia: persatuan yang tidak meniadakan perbedaan, melainkan harmoni di dalamnya. Dengan refleksi sejarah, jelas bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan integrasi yang sejati—menghormati keragaman, menjamin kesetaraan, dan menolak diskriminasi—agar persatuan bangsa tumbuh di atas fondasi yang kokoh dan adil. Sesungguhnya integrasi telah terjadi sejak masa lampau di Nusantara. Terbukti dari berbagai hasil persilangan budaya, sebagaimana dicatat dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya misalnya. Namun kolonialisme lah yang memisahkan, dan zamrud khatulistiwa penuh warna ini terlalu indah untuk diseragamkan.
Era reformasi membuktikan bahwa apa yang diatur melalui Inpres 14 Tahun 1967 tersebut, merupakan sesuatu yang jauh dari semangat kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut inpres diskriminatif tersebut. Ini juga berarti berakhirnya pendekatan asimilasi prosedural ala orde baru terhadap orang Tionghoa di Indonesia.