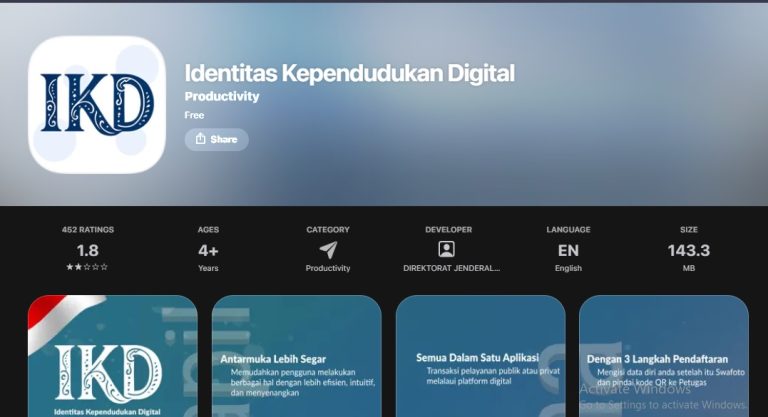Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945, wajah politik kewarganegaraan di Hindia Belanda mengalami perubahan mendasar. Jepang hadir dengan propaganda “Asia untuk orang Asia” dan menjanjikan pembebasan bangsa-bangsa Asia dari kolonialisme Barat. Namun di balik retorika tersebut, terdapat agenda militer dan ekonomi yang lebih dominan. Inilah bagian dari strategi penjajahan Jepang.
Propaganda Nasionalisme
Jepang memanfaatkan isu nasionalisme sebagai alat untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Janji kemerdekaan menjadi senjata propaganda utama, meskipun kenyataannya kontrol penuh tetap berada di tangan tentara Jepang. Bagi masyarakat pribumi, propaganda ini membuka ruang baru dalam kesadaran politik. Namun bagi kelompok Tionghoa, Arab, dan Timur Asing lainnya, situasinya lebih kompleks. Misalnya, surat kabar berbahasa Indonesia seperti Asia Raya memuat banyak artikel yang mendorong persatuan Asia di bawah Jepang, sementara media komunitas Tionghoa lebih diawasi ketat karena dicurigai pro-Tiongkok. Namun, patut diakui bahwa Jepang memberi ruang untuk berkembangnya nasionalisme Indonesia, yang sedikit banyak mempengaruhi terbangunnya konsepsi kewarganegaraan dalam taraf tertentu.
Perubahan Relasi Antar Etnis
Sebelum Jepang masuk, Hindia Belanda mengenal segregasi sosial yang ketat: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (termasuk Tionghoa dan Arab), dan Golongan Bumiputera. Masa pendudukan Jepang justru mendorong integrasi baru. Kepentingan logistik dan perang membuat Jepang harus merangkul berbagai kelompok. Bahkan, terjadi pertemuan dan integrasi antara peranakan dan totok Tionghoa, sesuatu yang sebelumnya sulit tercapai di bawah Belanda. Misalnya, organisasi pemuda yang dibentuk Jepang seperti Seinendan atau Keibodan beranggotakan lintas etnis, sehingga batas sosial kolonial Belanda mulai mencair.
Pada masa kolonial Belanda, terdapat Kantoor voor Chineesche Zaken, lembaga resmi yang mengurusi urusan komunitas Tionghoa. Ketika Jepang berkuasa, kantor ini diganti dengan Kakyo Han (dalam bahasa Mandarin: Hua Chiao Pan). Lembaga ini masih misterius karena minim penelitian akademik, namun catatan sejarah menunjukkan banyak tokoh Tionghoa ditangkap melalui struktur Kakyo Han. Salah satu contohnya adalah penangkapan tokoh-tokoh Tionghoa yang diduga pro-Kuomintang, terutama mereka yang terlibat dalam jaringan bantuan untuk Tiongkok dalam perang melawan Jepang. Laporan intelijen Jepang pada 1943 menyebutkan bahwa Kakyo Han aktif mengawasi sekolah, perkumpulan dagang, dan surat kabar Tionghoa.
Produk Hukum Jepang
Sistem hukum kolonial Belanda digantikan dengan Osamu Seirei (Undang-Undang masa Jepang). Regulasi ini mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk status penduduk. Namun, berbeda dengan Belanda yang menekankan kategori hukum berdasarkan ras, Jepang lebih menekankan kepentingan perang, sehingga struktur hukum bersifat militeristik dan represif. Salah satu peraturan Osamu Seirei yang terkenal adalah larangan penggunaan bahasa Belanda dan penutupan sekolah-sekolah Belanda, diganti dengan sekolah berbahasa Jepang. Hal ini menandai pergeseran orientasi budaya sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum dijadikan instrumen kontrol ideologis.
Sensus penduduk 1931 menunjukkan jumlah Tionghoa di Hindia Belanda mencapai 1.044.657 jiwa. Pada 1963, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.450.000 jiwa. Menariknya, proporsi antara peranakan dan totok tercatat 70:30, memperlihatkan dominasi peranakan dalam komunitas Tionghoa di Indonesia. Perubahan demografis ini turut mempengaruhi dinamika kewarganegaraan setelah masa kemerdekaan. Misalnya, dominasi peranakan mendorong tuntutan untuk lebih diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sedangkan kelompok totok cenderung masih menjaga ikatan budaya dan ekonomi dengan Tiongkok.
Kesimpulan
Pendudukan Jepang bukan sekadar babak baru kolonialisme, melainkan titik balik dalam sejarah kewarganegaraan Indonesia. Jepang meruntuhkan sekat-sekat kolonial Belanda, namun menggantinya dengan kontrol militer yang keras. Komunitas Tionghoa, yang sebelumnya memiliki posisi ambivalen di bawah Belanda, kini menghadapi situasi penuh tekanan. Pada saat yang sama, integrasi lintas etnis yang muncul di masa Jepang menjadi modal penting dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Contoh nyata adalah keterlibatan tokoh-tokoh dari berbagai etnis dalam organisasi bentukan Jepang yang kemudian menjadi basis bagi kader-kader politik dan militer Indonesia setelah 1945. Dengan demikian, masa pendudukan Jepang meninggalkan warisan ganda. Penindasan keras, tetapi juga pembukaan ruang bagi terbentuknya kesadaran kebangsaan yang lebih inklusif.
Puncaknya, ketika kelak dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau BPUPK. Penguasa militer Jepang tidak berkeberatan terhadap susunan anggota BPUPK yang demikian plural. Baik dari segi etnis, agama, hingga status sosial. Bahkan diantara 63 anggotanya terdapat 4 orang perwakilan masyarakat Tionghoa. Sehingga seharusnya mereka termasuk pendiri bangsa yakni Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oei Tjong Hauw, dan Oei Tiang Tjoei. Sayang hingga sekarang, justru mereka diasing-asingkan.@esa