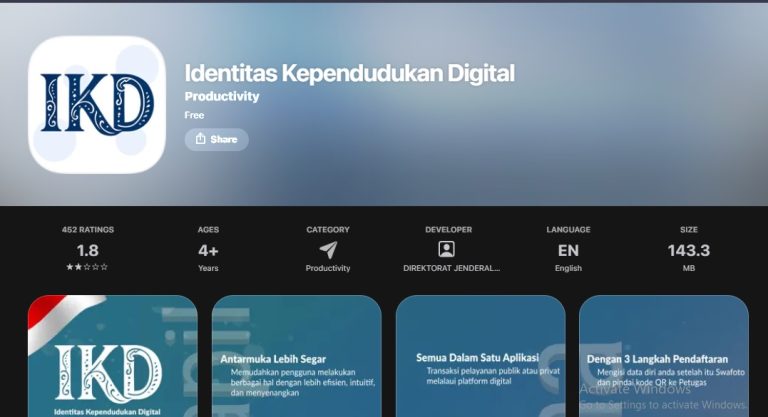Delapan puluh tahun merdeka, tapi pertanyaannya tetap: siapa yang sungguh merdeka? Negara masih sibuk mengatur kewarganegaraan sebagai status administratif. Menjadi sekedar identitas hukum, bukan kewarganegaraan dalam pengertian yang lebih hakiki. Kewarganegaraan adalah soal rekognisi penuh bagi seluruh warga negara, soal partisipasi dan distribusi. Mari kita renungkan kewarganegaraan kita dalam momen 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Bagi rakyat, secara praktis juga soal hidup dan masa depan. Anak-anak perkawinan campuran hingga saat ini, masih ditetapkan memilih pada usia 18–21 tahun. Usia yang berdasarkan praktik hukum mungkin dianggap sudah cakap hukum. Tapi mengapa kita tidak berkaca pada negara lain yang pada umumnya mulai memilih rata-rata di usia 22 atau lebih tua? atau mengapa tidak memanfaatkan berbagai penelitian terbaru terkait kedewasaan usia manusia?
Kajian neurosains kontemporer menegaskan bahwa batas usia dewasa hukum yang selama ini ditetapkan pada 18 tahun belum sepenuhnya sejalan dengan kematangan psikologis manusia. Laurence Steinberg (Temple University) menunjukkan bahwa prefrontal cortex—bagian otak yang mengatur pengendalian diri dan pengambilan keputusan rasional—baru mencapai kematangan penuh sekitar usia 25 tahun. Hal ini sejalan dengan laporan Lancet Psychiatry (Sawyer et al., 2019) yang mengusulkan perluasan definisi masa remaja hingga 24 tahun, karena transisi menuju kemandirian sosial dan emosional seringkali berlangsung lebih lambat daripada kematangan biologis. Harvard Center on the Developing Child juga menegaskan bahwa kapasitas executive function seperti perencanaan dan evaluasi risiko baru stabil pada usia awal hingga pertengahan 20-an. Dengan demikian, meski hukum positif banyak negara menetapkan usia 18 tahun sebagai dewasa legal, sejumlah pakar berpendapat keputusan besar—termasuk menentukan kewarganegaraan—lebih matang diambil pada rentang usia 21–25 tahun.
Bagaimana untuk Eks WNI?
Selain isu anak berkewarganegaraan ganda terbatas, perlu kiranya di usia 80 tahun RI direnungkan tentang eks-WNI. Sudah ada golden visa untuk mereka namun apakah negara tidak perlu menyiapkan naturalisasi khusus (yang dipermudah) bagi mereka? Mereka mungkin bekerja di luar tanah tumpah darahnya. Pada posisi-posisi strategis yang hanya bisa dijabat jika berkewargnegaraan setempat. Tapi jika suatu saat mereka ingin kembali, tidakkah ada jalan kembali yang lebih terbuka dan hangat?
Ironi ini semakin jelas ketika melihat data: ada 6–9 juta diaspora Indonesia di luar negeri, dan hampir 300 ribu pekerja migran resmi dikirim pada 2024. Mereka adalah wajah Indonesia di dunia, tenaga dan keringatnya menopang ekonomi, tapi sering dipandang sekadar “remitansi”, atau sumber elektabilitas. Sementara di sisi lain, momok loyalitas ganda terus diperkuat dan dirawat. Namun, dalam dunia yang kian tanpa batas, apakah ketakutan semacam ini masih relevan?
Terakhir, soal pendidikan kewarganegaraan. Kita harus kembali ke akar, yaitu membangun kesadaran dan membebaskan dari kebodohan. Menginjak usia kedelapan puluh tahun, ini juga harus menjadi pengingat kita semua bahwa hanya tersisa 20 tahun lagi. Bukankah kita punya mimpi Indonesia Emas 2045 tepat 100 Tahun kemerdekaan Indonesia. @esa