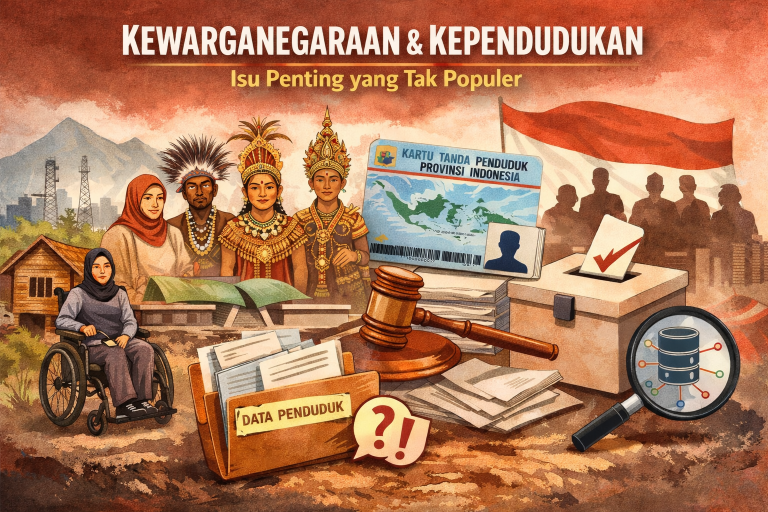Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memperluas basis pajak menimbulkan pertanyaan penting: apakah langkah ini menandai kemajuan dalam penegakan pajak, atau justru kemunduran dalam relasi kewarganegaraan? atau bisakah kita membentuk warga negara sadar pajak?
Warga negara tentu memahami bahwa pemerintah sedang mengejar penerimaan di tengah defisit fiskal dan perlambatan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa pajak bukan sekadar sumber keuangan negara. Pajak adalah simbol kontrak sosial, sekaligus bentuk partisipasi warga negara. Ia bukan semata-mata kewajiban.
Sebagaimana relasi kewarganegaraan yang bersifat timbal balik, partisipasi warga melalui pajak juga melahirkan harapan. Misalnya, pelayanan publik yang inklusif dan cepat, sistem yang bebas pungli, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika pemerintah terbukti menghadirkan hal-hal ini, maka perluasan basis pajak tak akan disambut dengan resistensi.
Baca juga: https://www.yayasan-iki.or.id/berita/08/12/2022/peduli-disabilitas-iki-dan-knd-berkolaborasi/
Ekstensifikasi dan Shadow Economy
Istilah shadow economy kerap digunakan untuk membenarkan kebijakan ekstensifikasi. Dalam praktiknya, istilah ini kerap merujuk pada sektor informal. Misalnya pedagang kecil, tukang ojek, pelapak daring, atau pengrajin rumah tangga.
Kelompok ini bekerja di luar sistem formal bukan karena ingin menghindari pajak. Mereka lebih sering terkendala akses, literasi, atau infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, bila negara menggunakan pendekatan represif pada kelompok ini, artinya negara berisiko mengkriminalisasi warganya sendiri. Bukan karena kesengajaan, tetapi karena keterbatasan.
Pendekatan seperti ini bertentangan dengan difference principle dari filsuf politik John Rawls dalam A Theory of Justice (1971). Rawls menyatakan, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya bisa dibenarkan jika manfaat akhirnya dirasakan oleh kelompok yang paling tidak diuntungkan.
Baca : https://www.jstor.org/stable/3749710
Sebagai contoh, gaji seorang menteri atau pejabat tinggi bisa lebih besar. Namun, hal itu dibenarkan sejauh mereka menciptakan kebijakan dan layanan publik yang meningkatkan kesejahteraan warga biasa, terutama yang miskin.
Dalam konteks perpajakan, sistem yang adil adalah sistem yang memberi ruang kepada kelompok lemah. Misalnya lewat tarif progresif, insentif bagi pelaku usaha kecil, serta pembebasan pajak minimum bagi pendapatan rendah.
Sebaliknya, bila ekstensifikasi malah menekan mereka yang tidak memiliki perlindungan, literasi, atau infrastruktur digital, maka ketimpangan itu tidak etis. Apalagi jika warga bahkan belum memiliki dokumen identitas hukum yang sah—padahal dokumen tersebut adalah pintu masuk ke hak-hak kewarganegaraan lainnya.
Membangun Kepercayaan, Bukan Ketakutan
Kepatuhan pajak tidak tumbuh dari rasa takut semata. Slippery slope framework (Kirchler et al., 2008) menyebutkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berperan sama pentingnya dengan kekuatan hukum. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik terhadap institusi fiskal masih harus dibangun untuk membentuk warga negara sadar pajak.
Jika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang keras, maka warga bisa merasa dicurigai hanya karena belum terdaftar. Pajak pun dilihat sebagai pemaksaan, bukan partisipasi. Relasi negara dan warga bergeser dari kemitraan menjadi dominasi.
Ketika Akses Tak Sejalan dengan Pajak
Fenomena ini juga tercermin dalam kasus komunitas anak muda yang bermain di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Pada Juni 2025, publik dikejutkan oleh unggahan media sosial yang menyebut adanya pungutan hingga Rp 1,9 juta terhadap komunitas permainan tradisional. Mereka bermain tanpa memakai fasilitas khusus.
Sebelumnya, komunitas yang sama juga pernah diminta membayar hingga Rp 6 juta per kegiatan (Kompas.com, 30 Juni 2025). Pihak GBK memang kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada transaksi yang benar-benar terjadi, dan kegiatan nonkomersial tetap diperbolehkan secara gratis.
Namun, kejadian ini tetap memunculkan pertanyaan penting di kalangan anak muda: jika pajak telah dibayar, mengapa ruang publik yang mestinya gratis tetap memunculkan pungutan? hal seperti ini tentu menghambat tumbunya warga negara sadar pajak.
Secara teknis, ini bukan kebijakan pajak. Namun, secara substansial ini menunjukkan kesenjangan antara kontribusi warga negara dan manfaat yang diterima. Keadilan fiskal bukan hanya soal tarif dan pelaporan, tetapi juga soal akses terhadap hak dasar. Termasuk hak atas ruang publik.
Ekstensifikasi yang Etis dan Inklusif
Ekstensifikasi pajak tetap penting. Namun, pendekatannya harus tunduk pada prinsip etika kewarganegaraan. Warga negara adalah subjek yang berdaulat, bukan objek penertiban. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus berdasarkan pemetaan kemampuan dan risiko fiskal masing-masing kelompok.
Negara perlu memperluas inklusi fiskal dengan insentif yang adil. Misalnya tarif lebih ringan bagi usaha mikro, insentif penghasilan rendah, kemudahan administrasi pajak, dan sistem yang ramah pengguna. Literasi dan pelayanan yang humanis akan menumbuhkan kepatuhan secara sukarela.
Sebaliknya, terhadap penghindar pajak kelas atas, negara perlu menunjukkan ketegasan. Jika pelaku usaha kecil ditekan, sementara pengemplang besar dinegosiasi atau diberi pengampunan, maka legitimasi sistem akan runtuh. Masyarakat pun akan bertanya: kalau semua yang belum bayar pajak dianggap mencurigakan, apakah negara sedang membangun kepercayaan atau ketakutan?
Dari Ketakutan ke Kepercayaan
Reformasi pajak bukan hanya soal peningkatan penerimaan. Ia adalah proses membangun ulang relasi antara negara dan warga. Pajak harus dilihat sebagai bentuk kepercayaan, bukan ancaman. Negara yang adil bukan hanya menarik kontribusi, tapi juga memberi jaminan hak.
Rakyat Indonesia adalah salah satu masyarakat paling dermawan di dunia. Mereka terbiasa berdana secara sukarela, termasuk melalui komunitas dan filantropi. Jika pendekatan pajak dibangun atas dasar kepercayaan, bukan tidak mungkin mereka yang masuk kategori shadow economy justru menjadi kontributor sukarela.
Bahkan, bila sistem memungkinkan mereka menentukan sendiri besaran kontribusi bulanannya, bukan tak mungkin partisipasi mereka melebihi ekspektasi. Kita bisa lihat di media sosial: begitu kepercayaan tumbuh, masyarakat bisa memberikan dukungan tanpa syarat.
Namun, bila pendekatan fiskal lebih banyak menumbuhkan rasa curiga daripada kepercayaan, maka yang muncul bukan kepatuhan, tetapi keterpaksaan. Dan sejarah telah berulang kali menunjukkan: keterpaksaan adalah fondasi paling rapuh bagi sebuah negara.
Lebih dari itu, bila pajak hanya ditarik lewat paksaan dan otoritas digunakan untuk menekan yang lemah, maka kita tengah bergerak mundur. Dari relasi modern antara warga dan negara menjadi pola lama relasi kawula–gusti. Dalam relasi semacam itu, penguasa bebas menentukan pungutan tanpa dialog. Pajak bukan lagi bentuk partisipasi warga, melainkan alat pemaksaan sepihak.@esa