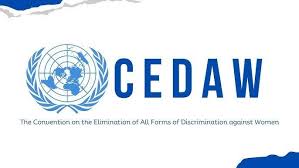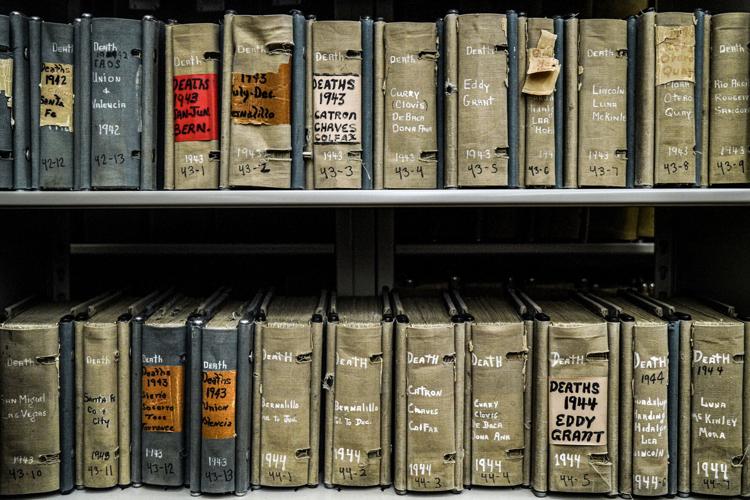Tahun 2025 menandai 41 tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Momentum ini menjadi pengingat penting bagi negara. Untuk mengevaluasi komitmen terhadap kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW adalah singkatan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
Salah satu upaya konkret untuk memperkuat mekanisme nasional adalah agenda monitoring dan konsultasi. Agenda yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Salah satunya diadakan bersama organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda ini menyoroti laporan periodik Indonesia kepada mekanisme hak asasi manusia internasional. Yakni CMW dan CEDAW, dengan fokus pada isu-isu seperti pekerja migran perempuan dan perkawinan anak di tingkat daerah.
Perspektif Pemerintah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa melalui Sidang ke-52 Komite CEDAW. Indonesia telah menyampaikan laporan periodik dan memaparkan berbagai kemajuan kebijakan nasional. Seperti pengarusutamaan gender dalam regulasi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pelayanan publik. Namun demikian, Komite CEDAW juga mencatat sejumlah tantangan yang masih harus diatasi. Seperti regulasi daerah yang belum responsif gender, tingginya kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan pekerja migran.
Secara khusus, Komnas Perempuan menyebut bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi masih banyak menemui kendala struktural dan kultural. Data menunjukkan kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan akses keadilan bagi korban belum optimal. Salah satu catatan penting adalah masih adanya ratusan peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam konteks tersebut, beberapa rekomendasi utama diajukan: mempercepat pengesahan regulasi pro-perempuan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG); memastikan partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan; dan menguatkan penyusunan laporan nasional yang inklusif masyarakat sipil.
Dengan demikian, peringatan 41 tahun ratifikasi CEDAW bukan sekadar merayakan lalu-lalang kebijakan bagi warga negara, tetapi memperkuat aksi nyata. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga HAM nasional, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menjadikan perjanjian internasional ini bukan hanya teks formal, melainkan instrumen yang nyata dirasakan oleh perempuan dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Momentum ini juga menandai perlunya sinergi lintas aktor—dari pusat hingga daerah—agar prinsip CEDAW benar-benar terwujud dalam kebijakan publik yang adil dan setara.@esa
Sumber: