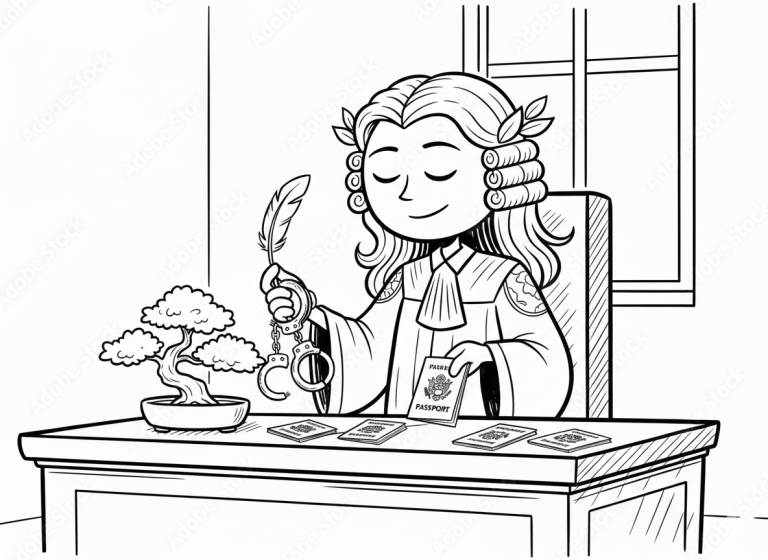Setiap beberapa tahun, jagat media sosial Indonesia kembali diguncang oleh unggahan bernada kebencian rasial. Polanya berulang: sebuah postingan provokatif viral, publik bereaksi, aparat bergerak setengah hati, lalu kasus perlahan menghilang tanpa kejelasan. Siklus ini menunjukkan bahwa intoleransi berbasis ras bukan sekadar persoalan individu, melainkan cermin dari masalah penegakan hukum yang jauh lebih dalam. Hal demikian bisa mengancam kewarganegaraan dan demokrasi kita.
Salah satu contoh yang pernah mencuat adalah unggahan Arif Kusnandar di Facebook yang menyerukan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa. Bentuk ujaran seperti ini bukan fenomena baru, namun dampaknya selalu sama: membuka kembali luka sejarah dan memicu ketakutan bahwa tragedi masa lalu dapat terulang. Demikian pula pada huru hara Agustus 2025 lalu, dimana aksi para pendemo disusupi para perusuh dan provokator. Termasuk penyebaran provokasi berbasis kebencian rasial di berbagai media sosial.
UU Penghapusan Diskriminasi dan KUHP
Penulis cukup ingat bahwa dalam sebuah diskusi yang digelar Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) beberapa tahun silam. Direktur Eksekutif Supriyadi W. Eddyono menggarisbawahi bahwa pernyataan semacam itu bukan hanya ofensif, tetapi juga melanggar hukum. Mulai dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hingga pasal 156 dan 157 KUHP. Namun ia menekankan bahwa regulasi ini tidak dibuat semata untuk menghukum pelaku. Aturan tersebut hadir sebagai alat rekayasa sosial: untuk mencegah diskriminasi berulang, meredam potensi kekerasan massal, bahkan mencegah arah yang mengarah pada genosida.
Masalahnya, menurut ICJR, hukum yang ada sering kali hanya menjadi teks di atas kertas. Dalam pemantauan lembaga itu sepanjang 2013–2015, tidak ada satu pun kasus penyebaran kebencian berbasis ras yang benar-benar diproses hingga pengadilan. Hanya beberapa kasus yang mencapai tahap penyidikan, dan itupun tanpa tindak lanjut yang jelas. Bahkan perkara besar seperti Obor Rakyat berjalan amat lambat. Temuan ini mengindikasikan kecenderungan yang mengkhawatirkan: aparat penegak hukum tampak enggan menuntaskan kasus-kasus diskriminasi rasial.
Konsekuensi Lemahnya Penegakan Hukum
Ketidakseriusan ini bukan hanya soal kelalaian administratif—ia membawa konsekuensi jauh lebih besar. Ketika ujaran kebencian dibiarkan tanpa konsekuensi, ia dengan cepat berubah menjadi preseden sosial. Publik membaca ketidakjelasan penegakan hukum sebagai sinyal bahwa diskriminasi adalah sesuatu yang bisa, dan boleh, dilakukan. Lambannya tindakan aparat berpotensi “menguburkan” pasal-pasal anti-diskriminasi yang sudah ada, menjadikannya instrumen hukum tanpa kekuatan.
Bagi ICJR, dampaknya terhadap demokrasi sangat nyata. Demokrasi hanya bisa hidup dalam ruang yang aman bagi seluruh warganya, tanpa memandang ras atau etnis. Ketika kelompok tertentu menjadi sasaran kebencian yang tidak ditindak, nilai kesetaraan warga negara menjadi rapuh. Pelaku kekerasan merasa diberi angin, sementara kelompok yang diserang dipaksa hidup dalam kecemasan. Ini adalah kondisi yang dapat merusak tatanan demokrasi secara perlahan namun pasti.
Supriyadi menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat reaktif. Ia harus menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun masyarakat yang bebas dari diskriminasi. Artinya, aparat tidak cukup hanya menunggu laporan atau viralnya sebuah kasus, tetapi perlu menunjukkan bahwa hukum benar-benar hidup dan bekerja.
Di tengah era media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan provokasi, tantangan semakin besar. Namun justru di sinilah pentingnya konsistensi penegakan hukum. Negara tidak hanya dituntut untuk menghukum mereka yang melanggar, tetapi juga untuk mengirim sinyal kuat bahwa kebencian berbasis ras bukan bagian dari identitas Indonesia. Karena ketika ujaran kebencian dibiarkan tumbuh tanpa batas, yang terancam bukan hanya korban langsung, melainkan demokrasi itu sendiri.
Mengenai SNP Penghapusan Diskriminasi Komnas HAM
Di sisi lain, penulis juga pernah berkunjung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi independen ini merupakan lembaga yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Untuk melakukan pengawasan seluruh upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Oleh karena itu, Komnas HAM sesungguhnya memikul peran sentral dalam menjaga agar ruang publik tetap bebas dari rasisme.
Dalam kunjungan penulis, pihak Komnas HAM menjelaskan bahwa mandat tersebut telah diperkuat melalui penyusunan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. SNP ini telah disahkan sejak 2020 lalu dan digunakan secara efektif sebagai pedoman nasional dalam menafsirkan serta menegakkan prinsip-prinsip anti-diskriminasi. Dokumen tersebut kini berfungsi sebagai kerangka operasional bagi Komnas HAM untuk memantau, menilai, dan memberikan rekomendasi terhadap setiap indikasi pelanggaran berbasis rasial.
Dengan landasan normatif yang kuat ini, menjadi semakin jelas bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga bentuk pengabaian terhadap amanat undang-undang dan kerja institusional Komnas HAM. Pada akhirnya, membiarkan rasisme berlangsung tanpa konsekuensi berarti merongrong fondasi demokrasi itu sendiri—yaitu jaminan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.@esa