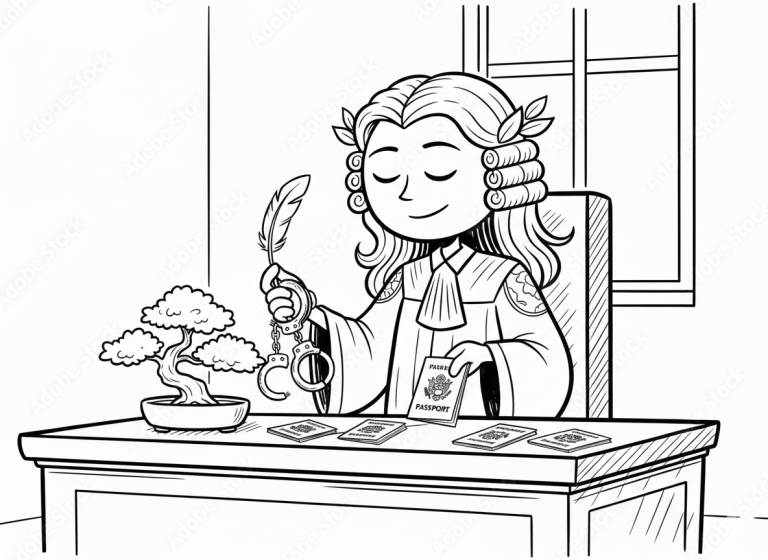Hak untuk bekerja merupakan bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 maupun instrumen internasional. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun praktik diskriminasi usia—sering disebut ageism—masih marak di berbagai lowongan kerja Indonesia. Di mana batasan usia sering diberlakukan secara eksplisit dan menghambat akses kerja secara adil.
Respons Pemerintah
Pemprov Jawa Timur memimpin inisiatif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan diskriminasi usia dalam rekrutmen. Kebijakan ini kemudian disusul oleh SE Menaker Nomor M/6/HK.04/V/2025. Penekanan SE adalah bahwa batas usia hanya diperbolehkan jika berkaitan dengan syarat fisik yang esensial dan tidak menghilangkan kesempatan kerja.
Kebijakan ini merupakan langkah positif sebagai representasi hukum yang berpihak pada prinsip kesetaraan. Namun, mengingat SE sifatnya administratif, kebijakan ini belum memiliki daya paksa kuat tanpa dukungan sistem pengawasan dan sanksi yang jelas.
Perspektif Internasional
Pertama, Universal Declaration of Human Right (Pasal 2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak tanpa “status lainnya.” Pernyataan ini dapat ditafsirkan mencakup usia, seperti dikemukakan oleh Craig Mokhiber (mantan pejabat senior OHCR –Office of the High Commissioner for Human Rights). Merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM di seluruh dunia.
Kedua, Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tegas melarang diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk bentuk yang merugikan kesempatan kerja secara substansial.
Praktik Efektif di Beberapa Negara
Amerika Serikat, adalah salah satu negara yang memiliki Age Discrimination in Employment Act (ADEA) sejak 1967. Aturan ini melindungi pekerja usia 40+, dan dipantau berdampak signifikan terhadap perekonomian—pada 2018, pekerja 50+ menyumbang sekitar 40% PDB dan mendukung jutaan pekerjaan. Sementara pemerintah Jepang, telah mendorong penghapusan batasan usia dalam lowongan, sebagai respons terhadap penuaan populasi.
Di sisi lain, Uni Eropa memiliki Council Directive 2000/78/EC yang melarang diskriminasi berbasis usia, dengan pengecualian minimal untuk pekerjaan yang menuntut syarat fisik khusus.
Ketiga praktik ini menunjukkan bahwa regulasi tegas tidak hanya adil, tapi juga mendukung produktivitas warga negara secara ekonomi.
Data Kontekstual yang Menjadi Alarm
Menurut data BPS (2023), sekitar 53,93% lansia di Indonesia masih aktif bekerja, sebagian besar di sektor informal—pertanian di pedesaan dan manufaktur/jasa di perkotaan. Banyak dari pekerja lansia ini hanya memperoleh upah rendah: 32,24% menerima upah minim, dan lansia perempuan—sekitar 57,53%—menerima gaji sangat rendah, dengan rata-rata gaji Rp 1,18 juta per bulan.
Pada 2021, sebanyak 97,94% pekerja lansia masih berada di sektor informal, dengan lebih dari 60% berstatus pekerja mandiri—seringkali karena keterbatasan kesempatan dalam pekerjaan formal. Sedangkan per Februari 2024, terdapat sekitar 7,1 juta orang usia di atas 15 tahun yang tidak bekerja, di mana kelompok usia 45–49 masih mengalami tingkat pengangguran tinggi, seperti 312 ribu orang dalam rentang 45–49, dan 202 ribu orang usia 60+ masih menganggur. Praktik batas usia dalam rekrutmen memperparah masalah ini, mengabaikan individu yang berpengalaman dan produktif.
Membangun Pasar Kerja yang Inklusif
Diskriminasi usia sejatinya merugikan potensi bangsa. Sekalipun di tengah bonus demografi, menutup akses kerja terhadap kelompok usia tertentu berarti menyia-nyiakan sumber daya manusia produktif. Beberapa rekomendasi bisa ditawarkan sebagai solusi. Pertama, penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengikat dan mencakup mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap diskriminasi usia. Kedua, fokus pada pelibatan lebih banyak lansia di sektor formal, memberikan pelatihan dan perlindungan sosial untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Ketiga, promosi inklusivitas dalam rekrutmen yang menilai kemampuan dan kompetensi—bukan usia.
Hak atas pekerjaan bukanlah soal angka usia, melainkan tentang kemampuan, pengalaman, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jika Indonesia ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, menciptakan sistem ketenagakerjaan yang non-diskriminatif bukanlah pilihan—melainkan keharusan.@esa